
IDB’s strategic position for the unity and integrity of ummah
oleh: NATAN.D.CARDTERD.WANIMBO
The ideals of social welfare and human solidarity, along with the belief in the oneness of God and the Prophetic messages, hold the highest level of cognition in the Quran. The Islamic philosophy and framework of political economy are built around these unique foundations. The principles and instruments so developed around these foundations pervade the Islamic political economy both in its domestic aspects as well as in global perspective. Human solidarity that emanates from the belief of mankind in the one true God, as Islam has inspired, is given a concrete form through the idea of Islamic economic co-operation and integration in diversified world.
The study of development co-operation in Islamic perspective requires the implementation of the normative and positivistic aspects of the Islamic ethico-economic principles to this area. First, the idea of Islamic economic integration must be enforced in the world nation of Islam, known as ummah. It has then to take rational and meaningful shape in terms of institutions and policy-theoretic foundations that can mobilize resources among the Islamic countries. The idea of Islamic economic integration must then subsequently evolve into global ethico-economic model of development and development co-operation. Thus, the human felicity that Islam bestows on mankind is extended to comprehend all of mankind, not just the Muslims and the Islamic nations.
Considerations of the Islamic ethico-economic foundations of socio-economic development, development financing and co-operation, are the principal areas that need to be studied in the context of world development in contemporary times. This evokes deep ethical parameters of development, new forms of institutions and concepts of the world order, and new dimensions in thought and social change. All these need to be studied seriously now, at a time when the world order is undergoing profound changes. The communist social facade is fast crumbling under the inscrutable human demand for greater freedom and social justice. The capitalist economies are fast transforming into welfare states by incorporating conditions of distributive equity as a socialization goal. The world economies are thus fast converting into mixed economies. Within this great transformation process, the moral and material needs of mankind are seeking expression in alternative paradigms and world views.
These phenomena of change in the social and thought processes apply particularly to developing countries, which have been long left out in the economic, catch up drive. The question remains to be examined as to where the fountains of new life and promise lie for these countries under alternative paradigms of thought and socio-economic development. Such questions and their bearing on the ethical and material tempo of development must be taken up at a juncture when United Nation’s today has entered its Fifth Development Decade and as the world launches into the third millenium to rediscover humanity.
Such are the questions and their proposed answers that are covered in this volume from Islamic perspective. The claim and rationale is throughout then made, that the Islamic worldview of change and order provides a unique “weltanschauung”. The universality of this alternative as it applies to all mankind and which can be rationally examined under the microscope of normative and positivistic criteria of investigation, makes the Islamic approach a venue for examination and study. This work makes this Islamic workview a unique one, in contrast to the idea of ethical relativism and cultural pluralism-based theories of socio-economic development, because the source of Islamic development concept are the Quran, the traditions of Prophet Muhammad sunnah, the analogy for deriving rules from these fundamental sources of knowledge through syllogistic deductionism ijtihad and qiyas, which all of these together are cast in the Islamic Laws, shariah.
Development of Islamic Financial Instruments
The history of Islamic economic co-operation and of the development finance institutions has began with established the first modern Islamic bank in a small city of Egypt, Mit Ghamr. Then, the First Islamic Conference of Foreign Ministers decided to establish a General Secretariat of the Organization of Islamic Conference (OIC) in March 1970.
The year 1974 saw the establishment of an Islamic Solidarity Fund at the OIC to promote economic co-operation among the Islamic countries. The establisment of the prime Islamic development finance organization, the Islamic Development Bank, also took place in 1974. The resources of the bank would be made up of subscribed shares of member countries of OIC and the operations of the bank would be guided by shariah in developmental direction. IDB is the first international aid organization that gift loan without interests. Then, established Dubai Islamic Bank, Faisal Islamic Bank, Kuwait Finance House, Jordan Islamic Bank, Qatar Islamic Bank, Bahrain Islamic Bank, Iran Saderat Bank and Indonesian Muamalat Bank. These finance institutions grow and would developed the Islamic countries.
 The Islamic Development Bank had adapted a combination of project identification, project financing and trade financing methods to promote socio-economic development potential in its membership. It also uses instruments such as resource mobilization through share capital, secondary market instruments in conformity with shariah. Being a development finance institutions, IDB’s objective criterion can be seen to be equitable distribution and mobilization of a maximum level of resources to its membership utilizing the instruments at its disposal. In the area of project financing the principal instrument are : Loan Financing, Technical Assistance, Equity Participation with mudarabah/musharakah, Line of Equity, Leasing and Line of Leasing, Installment Sale, Profit-Sharing, Foreign Trade Financing, Special Assistance and Capital Market Operations.
The Islamic Development Bank had adapted a combination of project identification, project financing and trade financing methods to promote socio-economic development potential in its membership. It also uses instruments such as resource mobilization through share capital, secondary market instruments in conformity with shariah. Being a development finance institutions, IDB’s objective criterion can be seen to be equitable distribution and mobilization of a maximum level of resources to its membership utilizing the instruments at its disposal. In the area of project financing the principal instrument are : Loan Financing, Technical Assistance, Equity Participation with mudarabah/musharakah, Line of Equity, Leasing and Line of Leasing, Installment Sale, Profit-Sharing, Foreign Trade Financing, Special Assistance and Capital Market Operations.
On the other hand, apart form economic co-operation under OIC, in several cases, Islamic countries are found to belong to more than one regional economic co-operation arrangement. For example, the Islamic countries merged into interregional or regional organizations. The interregional organization like OPEC, OAPEC, APEC, RCD and TPA. The African regional co-operations are ECOWAS, UDEAC, ENTENTE, NBA, OAU, PTA, CEAO etc., and the Asian regional co-operation like ASEAN, GCC and SAECS/SAARC. The common objectives have been trade liberalization, common tariffs on foreign export, joint-ventures, coordination of monetary policies, particularly in the Franc area African Islamic countries, and long-term plans for industrial development, industrial complementary, agricultural development and water resources development. Many of these regional co-operation arrangements also fall within the United Nations System of economic co-operation integration among developing countries. In fact, each of these countries in different regional economic co-operation in member of OIC and IDB.
Striving for the unity of ummah
The nexus of economic co-operation groupings influencing Islamic countries point to the inevitable common objectives of regional economic co-operation among Islamic countries. This fact is recognized by OIC. It makes the co-operation and integration schemes a globally linked regional co-operation system. Yet it is clear that none of these regional groupings need to abide by the Islamic financing goals of OIC and IDB when transacting as partners in projects not sponsored by the IDB. This obviously results in a loss of efficiency and breeds conflict of objectives and management of project between those sponsored by IDB and those sponsored by regional grouping. The concept of linked regional economic co-operation and integration as the formative edifice of global Islamic economic co-operation and integration is thus thwarted or made ineffective. It has been pointed out that this is indeed what happened when industrial complementary is lost, when the same country belongs both to OIC membership as well as to different grouping. This led to adoption of competing trade policies by OIC/IDB members in order to gain access to Northern markets.
Also, co-operation between IDB with the UNCTAD, the World Bank, the Asian Development Bank, International Monetary Fund and the African Development Bank, make overlap on the co-ordination goal and role of OIC and IDB because conflicting interests are face. For example, if one were to give Islamic communal economic co-operation and integration foremost priority, then one of the external sector policies that must be promoted would be trade liberalization among the Islamic countries in a regionally linked framework. Islamic countries within their regional groupings in Islamic economic co-operation must also levy a common tariff on specific import of tradables from countries outside the Islamic economic union while they liberalize trade between themselves. These prescriptions for the Islamic countries, although necessary for the establishment of Islamic economic co-operation, would obviously be an area of conflict between IDB and other international development organizations. In the area of industrial development, the Islamic approaches based-on profit sharing and equity financing, which are preferred by IDB, will be in conflict with the interest-bearing loan financing approaches of other international development organizations.
The ambiguous membership of Islamic country and un-autonomy of IDB are the key of these problems. To solve the problems, Islamic countries must be firmly united in one development organization. And the IDB could not co-operation with another international capitalistic development organization. Wealth of natural resources and human resources of Islamic countries, insya Allah afford to manage and self-developed on all Islamic countries. Great self confidence and autonomous of Islamic co-operation are the principal capital. Thus, Islamic countries, because of their large number and vast market potential, together with good prospects for economic complementary, can become a self-reliant trading bloc by themselves. This would require a period of import protection from countries outside the Islamic bloc while the latter promotes free trade within itself. Some problem will still be posed due to the lack of investments during the adjustment period of transformation to a full-fledged Islamic economic union. Liquidity will not be suddenly withdrawn from Eurocurrency markets by the capital surplus oil producers as long as proven investments potentials are not there.
Hence, in such an interim period, foreign investment must be invited into Islamic countries. In an Islamic economic union, these investors would be required to operate on the basis of equity participation, interest-free economy, a two-tier tariff system, a zero tariff between the Islamic countries and a nominal tariff on other countries’ imported good. Foreign investors would still have much to gain, as equity participation is usually accompanied with attractive tax rebates. They would also enjoy free access to the large markets of Islamic countries. An equity-based economy can continue in the face of price stabilization, non-deflationary conditions and growth of the private sector. The gradual elimination of interest rates in Islamic economies, their replacement by profit-sharing, the openness of Islamic countries to each others’ trade, and the setting of appropriate exchange rates, are the conditions that would favor a transition to a non-inflationary growth regime. This would generate attractive conditions for foreign investors to locate in Islamic economies.
In view of the goals of distributive equity of an Islamic politico-economic system, IDB would have to undertake many more projects in the social sector, such as, the financing of enterprises for the elimination of poverty and unemployment, self-reliant development for the Islamic countries in trade and industrial development, financing of appropriate institutions for the restructuring of the economic systems in accordance with shariah.
The model of Islamic economic co-operation must be a union system, and global Islamic politico-economic integration must be done. When viewed in this way, IDB would be required to play a key role in formulating the sosio-economic planning of its member countries. While the IDB do exist presently, it is important to see how it can be used most efficaciously for the common weal, unity and integrity of ummah. *** (Winner of IDB Silver Jubilee Essay Competition 2000)
Senjakalanya Budaya Baca, Memupus Terbitnya Tradisi Tulis
“Reading make a full man, conference a ready man, and writing an exact man”
(Francis Bacon, 1561-1626)
“A writer is not so much someone who has something to say as he is some one who has found a process that will bring about new things he would not have thought of if he had not started to say them”
(William Stafford, writing The Australian Crawl)
Perguruan tinggi dan mahasiswa adalah dua elemen yang tak terpisahkan. Keduanya merupakan subyek yang mempunyai peran strategis untuk suatu perubahan dan perbaikan. Slamet Sutrisno (1996) menyebutkan bahwa perguruan tinggi, sebagai komponen baku dalam sistem pendidikan tinggi , harus menjadi tempat semaian pikiran dan gagasan baru. Sementara itu Babari (1996) memandang mahasiswa sebagai calon tenaga ahli yang harus disiapkan dan mempersiapkan dirinya untuk menjadi kekuatan penalaran yang bertindak atas dasar kemampuan berpikir analitis dan sintetis. Mahasiswa sebagai manusia penganalisa bukan semata-mata pemburu ijazah namun penghasil gagasan atau ide yang disajikan dalam bentuk pemikiran yang teratur, sistematis, mendalam dan benar. Dengan cara pandang semacam ini, mahasiswa akan menjadikan dirinya sebagai salah satu komponen kemasyarakatan yang menentukan karena memiliki kekuatan penalaran dan kemampuan pemikiran individual.
Pemikiran dan analisis, itulah yang menjadi kata kunci bagi perguruan tinggi dan mahasiswa. Kemampuan pemikiran dan analisis seorang mahasiswa menjadi prasyarat utama dibandingkan dengan teorema-definitif bidang keilmuannya sendiri. Bahkan, matang tidaknya seorang mahasiswa tergantung dari proses berpikir dan analisisnya. Tentunya kedua hal tadi harus senantiasa dibangkitkan dan digali sendiri oleh seorang mahasiswa. J. Drost (1996) mengatakan bahwa salah satu penentu kematangan seorang mahasiswa adalah penguasaan bahasa, khususnya bahasa Indonesia, yang dipakai saat bertutur maupun saat menulis. Tata bahasa dan ejaan harus dikuasai secara mutlak. Logika bahasa mencirikan cara berkomunikasi seorang mahasiswa. Sekali lagi, bernalar dan bertutur diperoleh dan dibentuk terutama lewat matematika dan bahasa. Matematika mengajar cara bernalar logis, sedangkan bahasa menunjang dan memperluasnya. Seorang baru bisa bernalar dan bertutur secara dewasa kalau ia menguasai ortografi, gramatika dan sintaksis bahasanya sendiri.
Kemudian, pemikiran dan analisis, yang didukung oleh penguasaan terhadap bahasa, tidak akan bisa diasah tanpa bahan baku yang tepat. Bahan baku yang dimaksud tidak lain adalah pre-information yang diperoleh dari sumbenya, yaitu kumpulan naskah dan buku-buku. Melalui buku, dipasok bahan baku yang dibutuhkan dalam proses penajaman pemikiran dan analisis. Dengan buku, proses transfer ide dan informasi menjadi lapang, sehingga terbentuklah suatu aliran pemikiran dan analisis yang laminar dari satu tempat ke tempat lain, dari satu generasi awal ke generasi berikutnya. Joseph Addison, seorang penyair dan sastrawan Jerman, berkata bahwa buku adalah harta karun yang ditinggalkan oleh para jenius besar bagi umat manusia, yang diwariskan dari generasi ke generasi, sebagai hadiah bagi mereka yang belum terlahirkan.
Baca-Tulis, Perintah Suci dan Peradaban Agung
 Ketika Nabi Adam moyang manusia diciptakan, Allah mengajarkannya nama-nama benda seluruhnya. Inilah proses pembacaan dan pembelajaran alam semesta yang pertama kalinya. Dari proses pembacaan itu, Adam mampu memahami esensi alam dan kemudian mampulah ia menuturkan pengetahuannya itu pada penghuni surga lainnya. Sulaiman, raja diraja dan utusan Allah lainnya, diberikan kemampuan membaca alam secara luar biasa, sehingga terjadilah dialog yang monumental antara dia dengan semut dan burung, yang tidak akan pernah terbaca oleh manusia lain. Selanjutnya Zabur, Taurat, Injil dan Al Quran adalah kalimat suci yang harus dibaca dan dijalankan oleh umat yang menerimanya. Bahkan, wahyu yang diterima Muhammad bin Abdullah, utusan terakhir, adalah mengenai Iqro’ dan Alladzi allama bil qolam, yang tidak lain tentang perintah Allah yang pertama-tama, yaitu membaca dan menulis.
Ketika Nabi Adam moyang manusia diciptakan, Allah mengajarkannya nama-nama benda seluruhnya. Inilah proses pembacaan dan pembelajaran alam semesta yang pertama kalinya. Dari proses pembacaan itu, Adam mampu memahami esensi alam dan kemudian mampulah ia menuturkan pengetahuannya itu pada penghuni surga lainnya. Sulaiman, raja diraja dan utusan Allah lainnya, diberikan kemampuan membaca alam secara luar biasa, sehingga terjadilah dialog yang monumental antara dia dengan semut dan burung, yang tidak akan pernah terbaca oleh manusia lain. Selanjutnya Zabur, Taurat, Injil dan Al Quran adalah kalimat suci yang harus dibaca dan dijalankan oleh umat yang menerimanya. Bahkan, wahyu yang diterima Muhammad bin Abdullah, utusan terakhir, adalah mengenai Iqro’ dan Alladzi allama bil qolam, yang tidak lain tentang perintah Allah yang pertama-tama, yaitu membaca dan menulis.
Peradaban-peradaban besar yang pernah ada di permukaan bumi, hampir pasti memiliki kemampuan komunikasi non verbal yang luar biasa pada jamannya. Artefak-artefak yang ditemukan di kota tua peninggalan wangsa Dravida, jejak-jejak jaman Babilonia-Mesopotamia, hyrogliph-nya bangsa Mesir Kuno, sampai relief-relief candi di Indonesia adalah bukti kemampuan peradaban-peradaban lama dalam usahanya menuangkan hasil pemikirannya, walaupun dengan cara yang sederhana. Fuad Hasan (2001) menyatakan bahwa di Mesir, terdapat patung berbentuk seorang yang duduk sambil memangku buku. Patung ini menggambarkan seorang yang sehari-hari bekerja sebagai pencatat berbagai peristiwa kemasyarakatan yang penting. Patung Sang Penulis (The Scriber) ini menunjukkan bahwa merekam secara tulisan sudah dikembangkan ribuan tahun lalu. Tradisi tulisan ini mulai berkembang sejak ditemukannya aneka bentuk huruf atau lambing yang dapat dirangkai sebagai kata atau cerita. Pendeknya tradisi tulis sudah dimulai jauh sebelum orang mengenal tulisan yang dihimpun sebagai buku.
Ketika kertas dikenal, penulisan dalam gulungan lembaran bertulis (scrolls) mulai berkembang. Berdirilah pula tempat-tempat khusus penyimpanan naskah-naskah itu, yang merupakan cikal bakal perpustakaan, mulai dari Mesir, Timur Tengah, Cordova, Asia Tengah sampai ke Cina. Walaupun begitu, pengguna dan pembacanya masih terbatas pada kalangan tertentu, intelektual, pemikir, pakar dan bangsawan.
Perubahan terbesar adalah ketika tradisi salinan tulisan tangan yang terbatas mulai ditinggalkan, dengan ditemukannya teknik cetak oleh Gutenberg pada abad kelima belas. Mulai saat itulah produksi buku meningkat, diikuti dengan meluasnya pengguna dan pembaca dari masyarakat umum.
Buku, peran dan permasalahanya
Tidak dapat dipungkiri bahwa meluasnya peredaran buku berpengaruh kuat dalam mengubah dan memajukan masyarakat. Edukasi dan informasi yang dibawa oleh buku mampu menggerakkan masyarakat kearah yang lebih baik. Suatu masyarakat yang menginginkan suatu proses kemajuan, harus menjadikan aktivitas membaca sebagai kebutuhan yang utama setelah pangan, sandang dan papan. Ironinya, proses kemajuan yang akan dituju itu tidak didukung oleh budaya dan minat baca yang tinggi oleh kebanyakan masyarakat, termasuk didalamnya mahasiswa.
Persoalan rendahnya minat baca ini sebetulnya merupakan akibat beruntun dari beberapa sebab. Formula yang diajukan Fuad Hasan, mantan Mendikbud kita, kiranya cukup tepat. Dikatakan, pemicu bagi bangkitnya minat baca ialah kemampuan membaca, dan pemacu bagi berseminya budaya baca ialah kebiasaan membaca, sedang kebiasaan membaca terpelihara oleh tersedianya bahan bacaan yang baik dan menarik. Nah, disinilah masalahnya.
Menurut laporan Masyarakat Perbukuan Indonesia (MPI), di Indonesia pada tahun 1995 hanya muncul 3500 judul buku, yang diterbitkan maksimal sebanyak 12 juta eksemplar dalam satu tahun. Jumlah ini kalah dengan oplah koran yang mencapai 14 juta sehari. Dari jumlah itu 60% buku pelajaran TK sampai SMU, 15% untuk perguruan tinggi, buku agama 10% dan sisanya 15% buku umum.
Disinyalir, produksi buku Indonesia paling rendah di Asia, jauh tertinggal dari produksi buku Malaysia, yang dengan jumlah penduduk 10% penduduk Indonesia, mampu menerbitkan 11.000 judul setahun. Harian Umum Media Indonesia pada bulan Mei 1996 menyebutkan bahwa jumlah judul buku baru yang diterbitkan di Indonesia hanya 0.0009% dari total penduduk. Artinya, 9 judul buku baru untuk setiap juta penduduk. Sangat jauh dibanding rata-rata negara berkembang (55 per sejuta penduduk) dan seperti semut dibandingkan dengan negara-negara maju (513 per sejuta penduduk). Data tersebut diolahnya dari Buku Statistik Tahunan UNESCO (1993) dan laporan UNDP (1994).
Laporan terbaru, yang disampaikan dalam pernyataan pers Ketua IKAPI bulan Mei 2001, bahwa produksi buku Indonesia menurun sejak krisis ekonomi dari 5500 hingga 6000 judul per tahun menjadi hanya 2500 sampai 3000 judul saja. Bahkan pimpinan perpustakaan nasional menyatakan bahwa dari sekitar 200.000 SD diperkirakan cuma 1% yang memiliki perpustakaan standar, dari sekitar 70.000 SLTP hanya 36%, dari sekitar 14.000 SMU cuma 54% dan dari sekitar 4000 perguruan tinggi hanya 60% yang memiliki perpustakaan standar. Untuk tingkat desa dan kecamatan, dengan sekitar 70.000 desa dan 9000 kecamatan, tak lebih dari 0,5% yang memiliki perpustakaan standar.
Disamping itu, bagi industri penerbitan buku di Indonesia, masih banyak persoalan yang mengemuka. Diantaranya menyangkut faktor mutu (isi maupun penjilidan) dan juga masalah distribusi. Apalagi mulai tahun 1980-an digunakan International Standard Book Number (ISBN). Secara aplikatif, penerapan ISBN berjalan bagus dan didukung oleh para penerbit karena memudahkan identifikasi buku melalui penomoran. Namun, keluhan masih bermunculan seputar mahalnya biaya pembuatannya. Misalnya, kalau suatu penerbit memperoleh tiga digit (berarti 1000 judul), maka diharuskan membayar Rp. 25.000,- kali seribu, atau dua puluh lima juta. Tentunya penerbit tidak mau terbebani biaya itu, sehingga kembali lagi konsumen yang terbebani. Tak urung, harga buku melangit. Belum lagi ditambah tingginya harga kertas dan biaya cetak.
Melonjaknya harga buku, membuat masyarakat semakin berat untuk mengkonsumsinya. Bukan aneh kalau ada penerbit atau pedagang yang melakukan pembajakan terhadap buku-buku yang ada (asli). Di satu sisi, pembajakan membuat buku murah harganya, namun disisi lain, penulis dan penerbit dirugikan dan penulisan buku baru dengan salary yang sesuai semakin langka.
Dengan demikian terbatasnya ketersediaan buku, maka tidak dapat disalahkan jikalau kebiasaan membaca menjadi hal yang langka pula. Tanpa ketersediaan bahan bacaan yang cukup, maka tentu saja semakin sulit untuk menumbuhkan pandangan bahwa membaca adalah suatu kebutuhan. Apalagi marak dan semakin berkembangnya media audio-visual, akan semakin berat pula tantangan yang dihadapi untuk menumbuhkan kebutuhan tersebut. Ironinya, rendahnya minat baca ini tidak hanya melanda anak-anak usia sekolah, namun juga mahasiswa yang harusnya menjadi pemeran dalam pencetus pemikiran dan analisis.
Proses Kreatif Menulis, Diawali Dengan Aktif Membaca
 Prisma (Februari 1981) menyebutkan komentar seorang pakar asing William Cummings tentang kondisi mahasiswa Indonesia, “Bahkan mereka yang menamatkan universitas di Indonesia tampaknya terdidik secara minimum, kurang dalam pengetahuan dasar, lemah dalam penguasaan bahasa asing, dan belum mengenal bacaan internasional yang menyangkut pengetahuan mereka. Tambahan pula para lulusan sering tidak memiliki moril dan kualitet yang sebanding dengan pengabdian terhadap masalah-masalah perkembangan nasional yang rumit.”
Prisma (Februari 1981) menyebutkan komentar seorang pakar asing William Cummings tentang kondisi mahasiswa Indonesia, “Bahkan mereka yang menamatkan universitas di Indonesia tampaknya terdidik secara minimum, kurang dalam pengetahuan dasar, lemah dalam penguasaan bahasa asing, dan belum mengenal bacaan internasional yang menyangkut pengetahuan mereka. Tambahan pula para lulusan sering tidak memiliki moril dan kualitet yang sebanding dengan pengabdian terhadap masalah-masalah perkembangan nasional yang rumit.”
Kekurangtahuan identik dengan kurangnya input yang dipahami. Kurangnya input lebih sering terjadi akibat rendahnya kebiasaan membaca. Dari sekitar 60% perpustakaan yang layak diseluruh perguruan tinggi di Indonesia, dapat dihitung berapa persen mahasiswa yang pernah berkunjung kesana, berapa persen yang sering datang, berapa persen yang membaca naskah non fiksi, berapa jumlah buku rata-rata yang dibaca mahasiswa selama sebulan, atau berapa persen intensitas mahasiswa memanfaatkan perpustakaan. Hampir pasti angka yang muncul berada pada level rendah.
Fenomena yang lazim terjadi, mahasiswa lebih banyak terlibat dalam kegiatan yang sifatnya sia-sia. Lebih sering berada di kantin, mereka lebih suka datang ke konser musik, mereka lebih senang jalan-jalan ke mall, atau ngerumpi tanpa arahan yang berarti. Bahkan kalau dilihat di tempat tinggalnya, entah di indekost ataupun asrama mahasiswa, lebih sering didapati koleksi album-album musik dalam bentuk pita kaset atau compact disk, dibandingkan buku-buku. Tentunya hal ini cukup memprihatinkan.
Walaupun tak bisa disalahkan bahwa bisa jadi hal itu adalah bawaan mereka sejak kecil yang tidak terdidik untuk gemar membaca, namun hal ini tidak bisa dijadikan pembenaran. Meski menurut penelitian periode paling formatif bagi manusia untuk dikembangkan kecerdasannya dengan pesat sekali ialah pada usia dibawah lima tahun, namun mestinya usaha pemupukan kesadaran (awareness raising) terhadap kebutuham membaca terus-menerus dilakukan. Hal ini tentu saja melibatkan semua komponen, mulai dari orang tua, keluarga, perguruan tinggi dan juga pemerintah. Kalaupun kebutuhan membaca sudah membaik di kalangan mahasiswa, namun tidak didukung oleh penyediaan bahan pustaka yang baik oleh perguruan tinggi atau tersedianya secara cukup dan murah bahan pustaka dari pemerintah, tentunya hampir mustahil kebutuhan itu akan bisa terpenuhi dengan layak.
Disamping itu, kinerja perguruan tinggi sebagai salah satu pemasok gagasan dan pembangun kemajuan di masyarakat juga harus diperbaiki. Saat ini, peran dan fungsi perguruan tinggi secara eksternal, yang berdampak bagi perubahan budaya masyarakat, tampak kurang berarti dibandingkan misalnya dengan peran politisi ataupun industriawan-bisnisman. Seharusnya, perguruan tinggi sebagai masyarakat ilmiah, harus bisa menjadi lokomotif bagi gerbong kemasyarakatan lainnya. Untuk mencapai hal itu, kapabilitas dosen dan mahasiswa harus dinaikkan, tentunya dengan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai penyangga bangunan ilmu pengetahuan. Dan yang terpenting adalah menjadikan aktivitas membaca sebagai hal yang dominan di kampus-kampus perguruan tinggi sebagai masyarakat ilmiah.
Jika budaya baca ini sudah menjadi suatu kelaziman, maka secara otomatis seorang mahasiswa yang mendapatkan informasi dan pengetahuan melalui aktivitas itu, akan sulit untuk tidak mengungkapkan apa yang dipahaminya kepada orang lain. Rasa keingintahuan yang tinggi akan diimplementasikannya dengan memberi tahu. Proses menerima dan memberi ini akan menjadi suatu kebiasaan yang hebat. Penyampaian itu tentunya akan banyak melibatkan transfer via bahasa tulisan, karena keterbatasan media verbal. Lewat tulisan, kendala ruang dan waktu akan lebih mudah teratasi. Jadi merupakan hal yang erat berkaitan antara budaya baca yang akan mengantarkan pada tradisi tulis yang baik.
Membaca yang baik, menurut Virginia Wolf, pembaca omnivora yang melahap dan memamah ratusan judul buku, seperti dikutip Muhidin (2000), adalah disertai dengan menulis. Dengan menulis seseorang mencoba bereksperimen sendiri dengan bahaya kata-kata dan kesukarannya. Atau menurut Paul Ricoeur, seorang filsuf poststrukrturalis, dengan menulis maka wacana lisan dibuat tidak lagi berubah melalui fiksisasi fisik oleh aksara melainkan pembakuan pikiran dan perasaan secara fisik dalam aksara.
Menulis, sampai saat ini masih dianggap sebagai hal yang sulit. Fenomena ketakutan mahasiswa ketika masuk masa penyusunan skripsi menjadi bukti rendahnya rasa percaya diri mahasiswa untuk sekedar menyusun kata-kata dan kalimat-kalimat. Padahal sebetulnya, menulis diawali dengan hal yang sederhana. Menuliskan apa yang dilihat sehari-hari adalah awal yang baik untuk memulai sebuah tulisan. Menuliskan peristiwa bangun tidur dan suasana pagi, menuliskan kemacetan dan menuliskan aktivitas pedagang asongan, bisa dicoba untuk memulai sebuah tulisan. Masih menurut Muhidin, penulis-penulis besar seringkali menuliskan hal-hal yang kita anggap sepele, namun ”kesepelean” itu yang biasa kita anggap sebagai “ketidakproduktifan” itu seringkali menggemparkan. Ahmad Wahib “hanya” menulis pengalaman religiusnya sehari-hari mencari Tuhan, berpacaran, kuliah dan tentang masyarakat. Namun catatan itu dilarang oleh MUI pada tahun 1984. Karl May, hanya menuliskan fantasinya berpetualang di daerah Wild West yang belum pernah sekalipun dilihatnya, namun ia bisa mengajak pembaca berkuda bersama Winnetou, menghirup udara padang pasir atau berburu beruang grizzli. Atau Pramoedya Ananta Toer yang harus merasakan “kenikmatan” bui karena tulisan-tulisannya.
Ilmuwan-ilmuwan besar semacam Ibnu Sina, menuliskan keahliannya dalam bidang kedokteran yang mengguncang Eropa yang saat itu masih berada pada jaman kegelapan. Ulama-ulama seperti Imam Syafi’i dengan Al Umm-nya, Imam Ghozali dengan Ihya Ulumuddin-nya atau Imam Bukhari dengan Kitab Shahih-nya, banyak dirujuk oleh kaum muslimin sampai saat ini. Politikus dan negarawan besar macam Karl Marx, Max Weber, Thomas Aquinas, Niccolo Machiavelli, sampai Soekarno menuliskan hal-hal yang menggemparkan dunia. Das Capital, Il Principle, sampai Di Bawah Bendera Revolusi mampu mengubah dunia.
Menurut Ignas Kleden, untuk membangun tradisi dan menulis, khususnya pada mahasiswa, harus tertanam wawasan budaya sebagai provokasi awal. Atau lebih tepat, dorongan ideologis harus dipupuk, sehingga bisa memotivasi mahasiswa rela menyendiri untuk membaca, meneliti, dan menuliskan pikiran dan penemuan-penemuan dari penelitian atau perenungan yang mau tak mau terhindar dan tersingkir dari pergaulan sosial dan pertemuan dengan orang untuk sementara waktu.
Penutup
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak hal yang melatarbelakangi rendahnya tradisi tulis di kalangan mahasiswa. Rendahnya budaya baca, yang merupakan derivatif dari langkanya bahan pustaka, mahalnya harga buku, rendahnya kualitas bahan bacaan, dan segala hal permasalahan dalan sistem pendidikan, merupakan hal yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Jika problem itu sudah bisa diatasi, maka pembangunan budaya baca dari diri mahasiswa baru bisa dijalankan secara efektif, sehingga proses kreatif menulispun akan secara langsung mengikuti.
Di luar negeri, pemakaian teknologi internet sebagai sarana membiasakan menulis lewat e-mail bisa ditiru sebagai cara baru yang layak dicobakan di Indonesia. Pemanfaatan perangkat IT ini merupakan ide yang bagus, mengingat semakin familiar-nya mahasiswa dengan media ini. Steve Kraus (1995) dari Bowling Green State University telah melakukan penelitian mengenai hal itu. Setiap mahasiswanya diharuskan untuk saling bercerita lewat class maling list atau listserv. Hasilnya cukup mencengangkan. Aktivitas on-line ini bisa mendongkrak aktivitas menulis mahasiswa dari tidak bisa menjadi bisa, dari bisa menjadi lancar, dan yang paling penting membuat para mahasiswa semakin percaya diri untuk menulis.
Terakhir, pandangan yang diungkapkan Muhidin menarik untuk disimak oleh para mahaiswa yang masih ‘takut’ menulis, “Jadi untuk menulis diperlukan suatu ketekunan. Dan saya orang yang paling tidak percaya bahwa membaca dan menulis adalah bakat dari sananya. Saya juga tidak percaya bahwa hanya mereka yang belajar di sekolah bahasa dan sastra yang bisa menulis dan membaca dengan baik. Non sense semua asumsi itu. Semua orang bisa, semua sama. Yang berbeda, mungkin, ia rajin dan kamu malas. Ia tekun dan kamu tidak.” Jadi, tinggal siapkan pena, kertas, dan kemauan yang keras. Lalu, mulai.*** (Juara Harapan Lomba Menulis Esai untuk Mahasiswa Tahun 2001 Yayasan Toyota Astra)
Kenaifan Hukum Kekekalan Energi
“Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan.
Energi hanya dapat diubah menjadi bentuk yang lain” (Hukum Kekekalan Energi)
Energi dan Pengekalannya
 Pemakaian kayu untuk pemanas atau angin maupun otot sebagai tenaga penggerak pada masa awal peradaban manusia, mengawali sebuah kajian tentang apa yang disebut sebagai energi. Archimedes, ahli matematika Yunani menggunakan prinsip mekanika dan membuat banyak peralatan penting. Diikuti ahli filsafat Aristoteles, Galileo, Newton, Huygen, Layden, Volta, Faraday, hingga sampai masanya James Joule (1818-1889), lelaki berbangsa Inggris yang pertama kali menyadari bahwa kerja menghasilkan panas dan panas adalah suatu bentuk dari energi. Jika kita mengangkat obyek berat, maka kita disebut melakukan kerja, karena kita menggunakan gaya untuk menggerakkan obyek. Sedangkan gaya adalah sesuatu yang beraksi pada obyek, dapat berupa tarikan atau dorongan. Maka kemudian energi disebut sebagai kemampuan untuk melakukan kerja.
Pemakaian kayu untuk pemanas atau angin maupun otot sebagai tenaga penggerak pada masa awal peradaban manusia, mengawali sebuah kajian tentang apa yang disebut sebagai energi. Archimedes, ahli matematika Yunani menggunakan prinsip mekanika dan membuat banyak peralatan penting. Diikuti ahli filsafat Aristoteles, Galileo, Newton, Huygen, Layden, Volta, Faraday, hingga sampai masanya James Joule (1818-1889), lelaki berbangsa Inggris yang pertama kali menyadari bahwa kerja menghasilkan panas dan panas adalah suatu bentuk dari energi. Jika kita mengangkat obyek berat, maka kita disebut melakukan kerja, karena kita menggunakan gaya untuk menggerakkan obyek. Sedangkan gaya adalah sesuatu yang beraksi pada obyek, dapat berupa tarikan atau dorongan. Maka kemudian energi disebut sebagai kemampuan untuk melakukan kerja.
Obyek yang bergerak mempunyai energi yang disebut sebagai energi kinetik. Energi mobil yang bergerak dapat meruntuhkan tembok batu bata. Sementara itu jika terdapat suatu gaya, maka disitu juga terdapat energi yang tersimpan, yaitu disebut sebagai energi potensial karena berpotensi untuk berubah menjadi energi kinetik. Salah satu energi potensial terpenting adalah energi kimia, yang tersimpan dalam komposisi kimia beberapa zat seperti tumbuh-tumbuhan, minyak, batu bara atau baterei listrik. Abdus Salam, peraih Nobel Fisika tahun 1979 mengatakan bahwa listrik, gravitasi dan dua jenis energi nuklir (gaya lemah dan gaya kuat), adalah gaya dasar. Energi listrik mudah diubah menjadi energi cahaya, bunyi dan panas.
Energi kimia itulah yang mengawali sebuah kesimpulan yang diambil oleh ahli kimia Perancis, Antoine Lavoisier (1743-1794) dan istrinya Marie Lavoisier, yang mengemukakan teori-teori dasar ilmu kimia, diantaranya Hukum Kekekalan Massa. Teori inilah yang dikemudian dikembangkan salah satunya oleh Einstein menjadi Hukum Kekekalan Energi. Teori ini menegaskan bahwa “Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah menjadi bentuk yang lain”. Apabila energi diubah, sisa senantiasa dihasilkan, namun jika ini diabaikan maka jumlah keseluruhan energi tidak berubah. Newton menggambarkan prinsip ini dalam sebuah alat mainan yang disebut ayunan Newton.
Kemunculan Teori
Encyclopedia of Science (1993) menyebutkan bahwa :
Energi menyebabkan berbagai peristiwa terjadi, diantaranya penangkal petir dan mengikat tali sepatu. Tanpa energi, tiada benda yang dapat hidup atau bergerak. Hewan menggunakan energi untuk berjalan dan berlari, tumbuhan menggunakan energi untuk membesar. Angin menggunakan energi untuk bertiup, ombak menggunakan energi untuk mengalun melintasi lautan. Apabila kereta bergerak, kereta itu menggunakan energi yang tersimpan dalam bahan bakarnya. Namun semua peristiwa ini tidak akan terjadi jika tidak ada gaya yang beraksi. Apabila energi digunakan, gaya juga turut terlibat. Gaya digunakan untuk pergerakan, dan untuk menghentikan pergerakannya. Gaya juga bertanggungjawab memecahkan dan mempertahankan keutuhan suatu benda. Tanpa gaya dan energi, tidak ada yang akan terjadi di dunia ini.
Pernyataan diatas mengisyaratkan bahwa energi dan gaya adalah peletak dasar dari semua kejadian yang ada di jagad raya. Bagi kalangan agamawan, tentunya hal ini merupakan suatu pengingkaran terhadap sifat Sang Pencipta yang abadi (eternal).
Jika ditelusuri, sebenarnya peletak dasar pemikiran ini adalah filosuf Yunani Aristoteles, yang mengatakan dalam bukunya Physics bahwa Everything that is in motion must be moved by something (segala sesuatu yang bergerak, pasti digerakkan oleh sesuatu). Sementara itu, para peneliti di Eropa mulai abad 16 bekerja dengan menjauhkan eksperimennya dengan konsep ketuhanan gereja (sekulerism – the theory of two swords). Hal ini dilakukan untuk menghindari berulangnya kasus dihukumnya Galileo dan Copernicus yang mengeluarkan kesimpulan eksperimen yang bertentangan dengan doktrin gereja. Saat itu muncul buku Sir Isaac Newton yang berjudul Philosophie Naturalis Principia Mathematica. Pada bagian akhir dari buku ini Newton mengatakan “cara yang sebaik-baiknya untuk memeriksa sifat-sifat benda adalah dengan mengambil kesimpulan dari eksperimen-eksperimen”. Kalimat ini menjadi metode bagi para peneliti pada jaman-jaman sesudahnya. Albert Einstein, seorang Yahudi Jerman, dalam persamaannya yang terkenal, E = mc2, mengatakan bahwa energi dan massa adalah sama, hanya berbeda perwujudannya. Menurutnya, massa sebetulnya adalah energi yang dipekatkan. Di kemudian hari, Einstein juga mengemukakan Teori Lapangan Dipersatukan. Dikatakannya, bahwa “energi mempunyai sifat atomik”, sementara “hukum fisik atom yang kecil harus sama dengan berlakunya pada benda-benda langit yang besar”, sehingga Teori Lapangan Dipersatukan mengumpulkan semua fenomena fisika menjadi satu skema, dan teori ini adalah “kunci dari alam semesta”.
Hal-hal inilah yang kemudian memunculkan banyak teori dan pernyataan para pendukung Teori Kekekalan Energi, seperti yang disebutkan dalam Encyclopedia of Science tersebut diatas.
Kenaifan Teori Pengekalan Energi
Sebenarnya telah banyak para ilmuwan muslim yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan Hukum Kekekalan Energi ini. Abu Ameenah Bilal Philips menyatakan dalam bukunya bahwa hukum ini mengandung makna menyekutukan Allah (syirik). Sementara itu, Prof. A. Baiquni mengkritiknya sebagai ilmu yang tidak Islami, sebab teori ini menganggap bahwa materi itu kekal. Diluar itu, beberapa ilmuwan muslim mengkhawatirkan kesalahan pemahaman dari umat Islam dari bunyi teks hukum tersebut, jika diajarkan tanpa penjelasan lebih lanjut.
Namun, para ilmuwan yang membenarkan hukum kekekalan energi ini mempunyai dalih mengenai sifat energi ini. Mereka mengatakan bahwa arti “tidak dapat diciptakan” dan atau “tidak dapat dimusnahkan”, tidak dapat disamakan dengan “tidak berawal” dan atau “tidak berakhir”. Selanjutnya, maksud dari “energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan” adalah bahwa “energi total selalu konstan”. Misalkan seseorang berdiri di puncak gedung WTC yang tingginya h dan menjatuhkan besi bermassa m. Sewaktu berada di puncak WTC, besi bermassa m mempunyai energi potensial EPpuncak dan energi kinetik EKpuncak = 0, atau energi total ETpuncak = EPpuncak + EKpuncak . Berdasarkan hukum kekekalan energi, maka energi total besi tersebut selalu konstan pada ketinggian manapun. Jika energi total besi di ketinggian 200 m dari permukaan tanah ET200 = EP200 + EK200, hukum kekekalan energi mengharuskan ET200 = ETpuncak. Demikian pula sewaktu besi mencapai tanah, EPtanah = 0, EKtanah = EPpuncak = ETpuncak = ET200. Artinya seluruh energi potensial EPpuncak berubah menjadi energi kinetik EKtanah. Sedangkan maksud “energi tidak dapat diciptakan”, dalam contoh di atas adalah bahwa tidak mungkin terjadi tanpa ada sumber energi dari luar, ET200>ETpuncak atau ETtanah>ETpuncak. Sedangkan maksud “energi tidak dapat dimusnahkan”, dalam contoh di atas adalah bahwa tidak mungkin terjadi tanpa ada energi yang berubah menjadi bentuk energi lain, ET200
Sebenarnya, semua perhitungan dan eksperimen mengenai konstannya energi awal dan akhir dari suatu sistem, hanyalah berdasarkan ASUMSI. Belum pernah ada eksperimen yang bisa membuktikan bahwa energi selalu konstan setelah dilakukan kerja. Jika kita membakar korek api misalnya, apakah energi kimia yang tersimpan dalam korek akan BERUBAH SELURUHNYA, dalam artian TEPAT SAMA dengan energi yang berwujud cahaya api, asap, dan panas. Apakah tidak ada kemungkinan bahwa terdapat “energi yang hilang”, entah dalam bentuk apa ? Pengukuran terhadap jumlah energi awal dan akhir pembakaran ini sampai saat ini sulit untuk dilakukan, bahkan jika diupayakan untuk mengisolasi sistem pembakaran korak api tersebut, apakah yang harus dipakai untuk mengisolasinya ? Apakah tidak mungkin ada “energi” yang masuk atau keluar melewati isolator itu ? Jadi sangatlah naïf jika dikatakan bahwa energi awal selalu TEPAT SAMA DENGAN energi akhir (konstan), kecuali sekedar ASUMSI. Bahkan dalam penggunaan notasi matematis, akan lebih tepat jika dipakai “≈”(setara), bukan “=“(sama dengan). Kesulitan-kesulitan matematis seperti ini juga diakui oleh Einstein, sehingga pengujian terhadap teori-teori fisika yang ada, belum dapat dilakukan.
Kalaupun kemudian hal-hal diatas diabaikan, atau DIASUMSIKAN bahwa energi awal dan akhir sebuah sistem adalah konstan, sangatlah naïf jika kemudian dikatakan bahwa energi itu kekal (eternal), tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Teks hukum kekekalan energi ini sebenarnya hanya berbicara mengenai “jumlah dan keadaan energi dalam sebuah sistem yang terbatas”. Misalnya sistem pembakaran korek api, sistem gerak ayunan Newton, sistem reaksi kimia atau sistem keteraturan jagad raya. Padahal semuanya itu hanya “sistem yang kecil, nisbi dan terbatas”, masih ada suatu “sistem yang absolut dan besar” yang melikupinya. Maka, akan lebih tepat jika yang terjadi adalah suatu proses pengawetan atau konservasi energi. Sehingga, hukum termodinamika pertama ini akan lebih tepat jika disebut sebagai Hukum Konservasi Energi, dengan bunyi teks “Energi suatu sistem selalu konstan, dan energi hanya dapat diubah (diawetkan) menjadi bentuk lainnya.” Karena jelas, jika dikatakan bahwa api itu mempunyai energi panas yang besar, bagaimana dengan kenyataan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim ketika dibakar dalam api yang menyala-nyala oleh Namrud. Padahal, Ibrahim justru merasakan bahwa api yang membakarnya dingin dan tidak membakar kulitnya. Bagaimana hukum kekekalan energi dapat menjelaskan fakta ini?
Atau ketika kita membakar korek api, menghasilkan panas dan cahaya, dapatkah kemudian kita mengubah cahaya dan panas tersebut menjadi sumber cahaya dan panas lagi (korek api). Padahal hukum kekekalan energi mengatakan bahwa energi hanya dapat diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Andaikan sekarang setiap orang di dunia ini melakukan proses pembakaran setiap benda, dan menghasilkan panas serta cahaya, dapatkah kita mendapati cahaya dan panas yang dihasilkan dari pembakaran itu kembali berubah wujud sesuai asalnya? Tidakkah lama kelamaan kita akan kehabisan sumber energi panas dan cahaya itu? Hal ini sebenarnya telah di jawab oleh Hukum Termodinamika II.
Lequent De Noi, ketua Bagian Fisika di Institut Pasteur dan Ketua Bagian Filsafat di Universitas Sorbonne, dalam bukunya Perjalanan Hidup Manusia, mengatakan :
Salah satu bentuk keberhasilan besar yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan modern adalah penghubungan hukum “Carnote-Clauzius”, yang dikenal pula sebagai hukum kedua dalam termodinamika dan dinilai sebagai kunci untuk memahami materi tidak hidup, dan penghitungan probabilitas. Boltzman, fisikawan besar, menemukan bahwa perkembangan materi tak hidup dan yang tidak dapat menerima kebalikan dari apa yang ditetapkan oleh hukum ini, bersesuaian dengan perkembangan menuju kondisi yang makin dan makin dekat kemungkinannya, yang mencerminkan keseimbangan yang makin bertambah dan ketetapan yang makin mantap. Demikianlah, alam semesta ini cenderung ke arah keseimbangan, yang tampak dengan makin lenyapnya ketidaksesuaian yang ada pada saat ini, untuk kemudian semua gerakan menjadi diam dan kegelapan yang utuh menyelimutinya.
Kemudian Edward L. menyebutkan :
Ada orang yang berkeyakinan bahwa alam semesta ini menciptakan dirinya sendiri, sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa kepercayaan tentang azalinya alam semesta ini tidak lebih sulit dari keperluan tentang keberadaan Tuhan yang azali. Akan tetapi, hukum kedua dari Hukum Termodinamika Panas menemukan kesalahan pendapat tentang azalinya alam semesta ini. Ilmu pengetahuan menetapkan dengan jelas bahwa alam semesta ini tidak mungkin bersifat azali karena ada perpindahan panas yang terus terjadi dari benda panas ke benda dingin. Tidak mungkin terjadi yang sebaliknya dengan kekuatan sendiri. Ini artinya, alam semesta ini bergerak menuju tingkat kesamaan panas seluruh benda dan darinya dikeluarkan sumber energi. Ketika proses itu selesai, tidak akan ada lagi proses kimiawi atau alami dan tidak akan ada lagi bekas kehidupan itu sendiri dalam alam semesta ini. Karena itu, kami berkesimpulan bahwa alam semesta ini tidak mungkin bersifat azali. Karena jika demikian, niscaya energinya telah habis semenjak lama dan seluruh gerakan dalam wujud akan terhenti. Demikianlah, ilmu pengetahuan, secara tidak sengaja, sampai pada kesimpulan bahwa alam semesta mempunyai awal. Karena itu, ia juga membuktikan akan wujud Tuhan. Karena jika mempunyai awalan, tentulah ia tidak mungkin memulai keberadaannya dengan dirinya sendiri. Ia harus memiliki Pemula, atau Penggerak pertama, atau Pencipta, yaitu Tuhan.
Matahari, yang dianggap sebagai sumber energi terbesar bagi penduduk bumi, menghasilkan reaksi fusi nuklir, terus menerus menghasilkan energi berupa panas dan cahaya. Namun, berdasarkan teori umur paruh, maka matahari akan mati suatu hari. Diperhitungkan sekitar 5000 juta tahun lagi, bahan bakar hidrogennya habis. Dari fenomena ini, timbul pertanyaan. Dari mana matahari mendapatkan energinya? Bagaimana ia menyimpan panasnya? Apa sumber energi dalam bintang-bintang? Jawaban yang paling memungkinkan adalah bahwa atom-atom matahari saling bertubrukan di bagian intinya yang panasnya 14 juta oC. Dengan adanya benturan yang besar, luas dan terus-menerus itu, lahirlah energi panas yang tiada bandingnya. Seperti diketahui, saat atom berbenturan, ia akan kehilangan sebagian dari intinya, yang berubah menjadi energi. Karena itu, setiap hari yang dilewati matahari, ia kehilangan sebagian tubuhnya walau sedikit. Matahari misalnya, kehilangan beberapa kilogram setiap harinya, dan bagiannya. Demikian juga dengan bintang-bintang.
Sementara itu, pernyataan bahwa materi berasal dari energi adalah salah. Suatu energi, sesuai kenyataannya sebagai energi, hanya dapat terwujud jika ada materi tempat ia timbul. Energi membutuhkan zat. Tanpa zat mustahil energi akan timbul.
Maka jelaslah bahwa energi timbul jika ada materi. Sedangkan materi diciptakan oleh Suatu Dzat, Dialah Allah, Sang Pencipta Yang Maha Kuasa. Dan jelas bahwa sifat azali hanya milik Allah, bukan sifat makhluk-Nya yang terbatas. Demikian yang disebutkan Allah :
 “Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri) ? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini ( yang mereka katakan). Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Rabb-mu atau merekakah yang berkuasa?”
“Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri) ? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini ( yang mereka katakan). Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Rabb-mu atau merekakah yang berkuasa?”
(QS. Ath Thuur [52]: 35-37).
Maha Kuasa Allah yang membuktikan kepada manusia ayat-ayat-Nya. ***
Bencana Dunia Akibat Logika Malthus
Semakin tinggi jumlah populasi pada suatu waktu, semakin banyak bayi yang dilahirkan dan mengakibatkan jumlah populasi pada generasi selanjutnya makin tinggi. Pertumbuhan populasi dunia akan semakin cepat mengikuti pertumbuhan eksponensial, sementara daya dukung lingkungan seperti ketersediaan lahan dan air bertambah mengikuti deret aritmatika. Pada suatu waktu, jumlah populasi akan melebihi ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan. (Thomas Malthus)
Sebuah Esai Yang Menggemparkan Dunia
Revolusi Amerika dan Perancis pada abad ke-18, membawa idealisme bagi orang-orang di Eropa untuk mengangan-angankan utopia-utopia. Mereka mengangankan suatu kondisi kesempurnaan manusia dan akan tibanya surga dunia. Diantara para utopis itu adalah William Godwin dari Inggris dan Marquis de Condorcet dari Perancis.
Godwin percaya, bahwa akan datang masa yang menjadi begitu padat oleh hidup sehingga tidak diperlukan tidur, tidak perlu mati dan kebutuhan perkawinan akan didesak oleh kebutuhan untuk mengemukakan intelek. Disamping itu juga tidak ada lagi penyakit, ketakutan, kesenduan ataupun dendam. Setiap manusia akan mencari kebaikan bersama dengan semangat yang tak dapat dilukiskan. Untuk meniadakan rasa takut, bahwa jumlah manusia jadi terlalu banyak sedangkan makanan tidak akan cukup, Godwin menulis, “bumipun akan tetap menghasilkan cukup untuk menghidupi penghuninya, biarpun manusia berkembang selama berjuta tahun lagi”. Ia berpikir bahkan keberahian berhubungan seks mungkin akan berkurang. Condoret mengusulkan, bahwa keberahian ini bisa dipenuhi dengan tidak mengakibatkan angka kelahiran yang tinggi.
Maraknya pemikiran utopis itulah yang kemudian dijawab oleh seorang pendeta muda dari Yesus College Cambridge, Inggris – Thomas Robert Malthus. Pada tahun 1789, di kala usianya 32 tahun, ia menerbitkan bukunya An Essay on the Principle of Population, sebuah esai tentang prinsip pertumbuhan. Di awal karangannya, Malthus mengemukakan dua pendirian dasar : pertama, bahwa makanan perlu untuk kehidupan manusia, dan kedua, bahwa gairah yang terdapat dalam seks adalah perlu dan keadaannya boleh dikatakan akan tetap seperti keadaan sekarang.
Dengan dasar pendirian tersebut, dengan sangat yakin, Malthus memaparkan postulat-nya yang terkenal :
“………bahwa kekuatan pertumbuhan penduduk nyata sekali lebih besar dari kekuatan dunia untuk menghasilkan nafkah bagi manusia. Jumlah penduduk jika tidak dikendalikan akan berlipat ganda menurut perbandingan geometri. Jika kita perhatikan angka-angka yang ada mengenai ini maka akan nyata, bahwa kekuatan yang pertama jauh lebih besar dari kekuatan yang kedua.”
Jika diutarakan dengan angka-angka, rumus Malthus akan menunjukkan pertumbuhan jumlah penduduk : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya, sedangkan persediaan makanan: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya.
Dari teorinya itu, lalu Malthus memberikan kesimpulan dan solusinya dengan dua hal utama, pertama pembukaan tanah lebih banyak dan dengan menganjurkan pertanian sebesar-besarnya, kemudian jika cara ini dipandang masih belum efektif dalam mengatasi kerawanan pangan, maka yang kedua adalah dengan pengendalian pertumbuhan penduduk. Pengendalian inilah yang sering disebut Malthus dengan “pengendalian langsung” yang ditujukan kepada “golongan positif” seperti pekerjaan-pekerjaan yang yang tak sehat, kerja yang berat, kemelaratan yang teramat sangat, penyakit, perawatan anak-anak yang tak baik, kota-kota besar, pes, epidemi; serta “golongan preventif”, yaitu pengekangan moral dan adanya cacat jasmani. Kesimpulan inilah yang menggemparkan dunia serta membuat golongan moralis agama dan sosialis radikal mengecam dan memakinya.
Melahirkan Imperialisme dan Kapitalisme
Ide Malthus untuk mengatasi rawan pangan inilah, yang mempengaruhi para pemikir Eropa saat itu, dan mulai memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada para penguasa Eropa dalam menghadapi bencana krisis pangan yang menghantui mereka. Apalagi setelah Malthus ‘memperbaiki’ kesimpulannya setelah menuai banyak kritik, dengan menerbitkan esainya yang kedua, yang menekankan “pengekangan moral” dan “menaruh keinginan hati untuk kebaikan umat manusia”, kelompok Malthusian dan Neo-Malthusiaan yang mendukungnya semakin kuat.
Pengaruh pemikiran-pemikiran Malthus atas ilmu pengetahuan alam boleh dikatakan sama dengan pengaruhnya atas ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Maka, baik Charles Darwin maupun Alfred Russel Wallace mengakui dengan terus terang, bahwa mereka dalam mengembangkan teori “evolusi dengan seleksi alam” harus berterima kasih kepada Malthus. Darwin menulis :
 Dalam bulan Oktober 1938, yaitu lima belas bulan setelah aku mulai penyelidikan yang sistematis, kebetulan aku, semata karena hiburan, membaca Pertumbuhan Penduduk karangan Malthus. Dan karena diriku telah bersedia untuk menerima perjuangan untuk hidup (suatu ucapan yang dipergunakan oleh Malthus) yang berdasarkan suatu pengamatan yang lama dan terus-menerus dari hewan dan tanaman yang berlaku dimana-mana, maka karangan ini dengan segera meyakinkan aku, bahwa dalam keadaan seperti ini jenis-jenis (variasi) yang serasi akan selamat sedangkan jenis yang tak serasi aakan hancur. Hasil daripada ini adalah juga sebuah teori yang dapat kupakai untuk bekerja.
Dalam bulan Oktober 1938, yaitu lima belas bulan setelah aku mulai penyelidikan yang sistematis, kebetulan aku, semata karena hiburan, membaca Pertumbuhan Penduduk karangan Malthus. Dan karena diriku telah bersedia untuk menerima perjuangan untuk hidup (suatu ucapan yang dipergunakan oleh Malthus) yang berdasarkan suatu pengamatan yang lama dan terus-menerus dari hewan dan tanaman yang berlaku dimana-mana, maka karangan ini dengan segera meyakinkan aku, bahwa dalam keadaan seperti ini jenis-jenis (variasi) yang serasi akan selamat sedangkan jenis yang tak serasi aakan hancur. Hasil daripada ini adalah juga sebuah teori yang dapat kupakai untuk bekerja.
Begitupun para ekonom dan pemikir peletak dasar kapitalisme, seperti John Maynard Keynes, mengelompokkan pemikiran Malthus bersama-sama dengan Locke, Hume, Adam Smith, Paley, Bentham, Darwin dan Mill. Walhasil, dari sinilah kemudian imperialisme dan kapitalisme global yang menghancurkan dunia mulai digulirkan.
Kerusakan Akibat Kapitalisme
Logika Malthus yang dikembangkan oleh Darwin dan diperkuat oleh para peletak dasar kapitalisme seperti Adam Smith atau John Stuart Mill, membuat bangsa-bangsa Eropa mulai mengadakan “penjelajahan samudera” untuk “menemukan sumber pangan dan tempat tinggal baru”. Maka lahirlah era imperialisme modern. Ketika metode imperialisme ini dihadang oleh semangat anti-penjajahan dari penduduk setempat di daerah jajahan, pemegang ideologi kapitalisme mulai mengganti metode imperialisme fisik ini dengan “penjajahan gaya baru”. Dari sini muncul suatu teori pembangunan yang diilhami oleh kesimpulan biologis-ekologis, yaitu Teori Ketergantungan. Teori ini menyatakan bahwa “suatu ekosistem yang stabil akan berusaha untuk mempertahankan stabilitas sistemnya dengan menyerap energi dari ekosistem yang lain”. Sehingga, untuk menjadi sebuah sistem yang ‘stabil’, negara-negara barat berusaha membuat suatu ketergantungan bagi negara-negara berkembang pada diri mereka dalam segala hal.
Tak pelak, petaka kesenjangan ketersediaan pangan melanda dunia. Menurut FAO pada tahun 2002, diperkirakan 815 juta penduduk di dunia menghadapi kelaparan dan kekurangan pangan kronis. Di antaranya, 777 juta penduduk bermukim pada apa yang disebut sebagai negara berkembang. Satu manusia meninggal setiap empat detik sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari kekurangan pangan. Limapuluh lima persen dari 12 juta anak-anak yang meninggal setiap tahun diakibatkan oleh kekurang pangan. Dalam lingkup kelaparan kronis di dunia, bayangan akan kekurangan pangan massal di daerah Sahara Afrika, di mana 12.8 juta orang di enam negara menghadapi risiko kematian dari kekurangan pangan karena busung-lapar, kekeringan dan kebanjiran. Terdapatnya konsentrasi jutaan penderita AIDS di daerah perdalaman negara-negara tersebut mengganggu pertanian dan memperburuk kekurangan pangan.
Pertemuan KTT Pangan FAO yang terakhir diselenggarakan pada tahun 1996, dan diakhiri dengan suatu pernyataan untuk menyeparuhi kelaparan di dunia pada tahun 2015. Kini, sepertiga jalan menuju tahun 2015, angka-angka resmi menunjukan hampir tidak ada kemajuan yang telah tercapai. Beberapa pejabat menyatakan bahwa dengan tercatatnya penurunan jumlah manusia yang menderita kekurangan pangan dan kelaparan sebesar enam juta jiwa pertahun dalam enam tahun yang lalu, mencerminkan suatu kemajuan. Angka ini harus meningkat ke 22 juta jiwa pertahun, bila target tujuan awal FAO ingin terpenuhi. Dengan keadaan seperti kini, pada tahun 2015, 122 juta manusia akan meninggal dari kelaparan dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengannya.
Pada sebagian besar dunia, termasuk lebih dari dua pertiga dari negara Dunia Ketiga, data FAO menunjukkan akan peningkatan dari kelaparan dalam dekade terakhir. Kekurangan pangan telah meningkat di Congo, India, Tanzania, Korea Utara, Bangladesh, Afghanistan, Venezuela, Kenya dan Iraq. Bila Cina tidak diperhitungkan, kekurangan pangan di dunia telah meningkat semenjak 1996. Keadaannya lebih parah di negara-negara seperti Malawi, Swaziland, Zambia, Zimbabwe dan Lesotho, di mana kelaparan bagi jutaan manusia adalah sebuah kepastian. Di Zambia, contohnya, ada sekitar 2,3 juta manusia yang membutuhkan bantuan pangan antara kini sampai dengan Maret 2003. Sebuah laporan FAO menyatakan “sudah tampak semua dasar tanda-tanda tekanan sosial” di negara ini. “Para penduduk mengambil langkah-langkah drastis, termasuk memakan makanan liar yang berpotensi beracun, mencuri hasil panen dan pelacuran, untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarganya.” Di Malawi, lebih dari 70 persen penduduknya tidak dapat memperoleh cukup pangan.
Sementara itu eksploitasi sumberdaya alam mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat parah diberbagai belahan dunia. Kerusakan dan degradasi lingkungan yang biasanya terjadi misalnya terbentuknya lahan kritis, akibat penggunaan lahan secara terus-menerus sebagai lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi banyak orang, terdapat antara lain di Afrika. Keadaan dapat diperburuk jika pengekploitasian lahan tersebut diiringi dengan iklim yang tidak menunjang, seperti banjir, sehingga mengakibatkan perubahan dari lahan produktif menjadi lahan tidak produktif. Di Mozambik, terjadi badai banjir ditahun 2000 dan 2001 diikuti dengan kemarau panjang di tahun 2002. Kemudian berkurangnya luas hutan, akibat pembukaan hutan untuk dimanfaatkan sebagai ladang atau hunian. Ditambah dengan penumpukan sampah akibat kegiatan domestik dan industri.
Sebagai negara kapitalis terbesar saat ini, Amerika Serikat terus-menerus mempertahankan eksistensinya dalam ‘merampok’ dunia. Sambil mempromosikan “perdagangan bebas”, pemerintah Amerika Serikat memberi diri mereka sendiri hak kebebasan untuk melakukan “dumping” hasil pertanian Amerika Serikat di negara-negara termiskin di dunia, meniadakan kesempatan kehidupan akan puluhan bahkan ratusan juta orang di Afrika dan negara-negara lain di dunia.
Kesalahan Logika Malthus
Dengan berbagai kerusakan yang timbul akibat Kapitalisme yang dilahirkan dari postulat Malthus, kita patut untuk memikirkan apakah betul logika yang dipakai oleh Malthus? Betulkah kondisi overload penduduk dunia akan terjadi? Akankah krisis pangan berlangsung?
Populasi dunia tercatat mencapai angka 5,77 miliar pada tahun 1996 dan para ahli memperkirakan jumlah ini akan terus bertambah dan mencapai 6 miliar pada tahun 1999. Katakanlah, setiap orang membutuhkan energi sebesar 3000 kkal perhari, maka setiap harinya diperlukan energi makanan sebesar 18 trilyun kkal. Jika jumlah energi dalam 100 gr beras giling sebesar 178 kkal, jagung giling sebesar 361 kkal, kentang 83 kkal dan tepung terigu 365 kkal, maka sebenarnya, kebutuhan pokok makanan penduduk dunia per hari sebesar 10 juta ton beras giling, atau 4 juta ton jagung giling, atau 25 juta ton kentang, atau 4 juta ton tepung terigu. Jumlah sebesar ini sebenarnya bisa dicapai dengan majunya pertanian dunia saat ini, belum lagi jika terdapat pangan subsitusi dan diversifikasi pangan.
 Fakta menunjukkan bahwa pangkal dasar dari sebab kelaparan di dunia bukanlah tidak adanya persedian pangan. Kekurangan pangan terjadi bersamaan dengan berlimpahnya bahan pangan di bawah kapitalisme. Hal ini berlaku baik untuk Amerika Serikat maupun negara-negara termiskin di dunia. Amerika Serikat menghasilkan 40 persen lebih pangan dari pada kebutuhannya, akan tetapi kelaparan sangat meluas dan 26 juta penduduk Amerika Serikat tergantung pada bantuan kupon pangan dari pemerintahnya. India telah mencapai surplus gandum sebanyak 59 juta ton, namun lebih dari setengah anak-anak di India hidup kekurangan pangan.
Fakta menunjukkan bahwa pangkal dasar dari sebab kelaparan di dunia bukanlah tidak adanya persedian pangan. Kekurangan pangan terjadi bersamaan dengan berlimpahnya bahan pangan di bawah kapitalisme. Hal ini berlaku baik untuk Amerika Serikat maupun negara-negara termiskin di dunia. Amerika Serikat menghasilkan 40 persen lebih pangan dari pada kebutuhannya, akan tetapi kelaparan sangat meluas dan 26 juta penduduk Amerika Serikat tergantung pada bantuan kupon pangan dari pemerintahnya. India telah mencapai surplus gandum sebanyak 59 juta ton, namun lebih dari setengah anak-anak di India hidup kekurangan pangan.
Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian yang disodorkan oleh kapitalisme dalam mengatasi krisis pangan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan produksi terus menerus dan pembatasan jumlah penduduk, adalah penyelesaian yang semakin menjerumuskan umat manusia ke dalam kesengsaraan. Padahal, permasalahan utamanya bukanlah dalam masalah produksi, namun adalah permasalahan DISTRIBUSI. Fakta menunjukkan bahwa sesungguhnya cukup tersedia sumberdaya bagi setiap penduduk dunia, hanya saja sebagian besar penduduk negara berkembang tidak memiliki sarana untuk mengakses sumberdaya tersebut.
 Allah memberikan jawaban semua itu dalam sebuah kerangka sistem ekonomi Islam yang utuh. Firman-Nya, “Dialah yang menciptakan untuk kalian semua, apa saja yang ada di bumi” (QS. Al Baqarah [2]:29). Politik ekonomi Islam tidak menjadikan pertumbuhan nasional sebagai asasnya dan tidak pula memperbanyak barang dan jasa yang menjamin terwujudnya kemakmuran hidup manusia, namun kemudian membiarkan mereka bebas mendapatkannya dengan semena-mena. Bukan pula untuk mewujudkan keadilan sosial atau sosialisme semu, dimana semua dibagi sama rata tanpa memperhatikan tingkat kebutuhan atau kekayaan. Namun politik ekonomi Islam bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer setiap individu, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan, serta terpenuhinya kebutuhan sekunder sebesar kadar kemampuan masing-masing individu. Maka, dasar ekonomi Islam adalah pendistribusian kekayaan, dengan mengatur cara penguasaan kekayaan dari sumbernya, yang kemudian diharapkan darinya akan muncul pertumbuhan ekonomi. Dan permasalahan distribusi ini telah diatur oleh hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan masalah kepemilikan, perolehan harta, pengelolaan harta, pengembangan harta, mata uang, jual beli dan distribusi kekayaan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman dalam Al Quran surat Al Hasyr ayat 7 : “…supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu.” Kehebatan sistem ekonomi ini telah dibuktikan oleh generasi-generasi Islam terdahulu. Wallahu a’lamu bishowab. *** - (Finalis Lomba Esai Ilmiah Harun Yahya Internasional Representative Indonesia)
Allah memberikan jawaban semua itu dalam sebuah kerangka sistem ekonomi Islam yang utuh. Firman-Nya, “Dialah yang menciptakan untuk kalian semua, apa saja yang ada di bumi” (QS. Al Baqarah [2]:29). Politik ekonomi Islam tidak menjadikan pertumbuhan nasional sebagai asasnya dan tidak pula memperbanyak barang dan jasa yang menjamin terwujudnya kemakmuran hidup manusia, namun kemudian membiarkan mereka bebas mendapatkannya dengan semena-mena. Bukan pula untuk mewujudkan keadilan sosial atau sosialisme semu, dimana semua dibagi sama rata tanpa memperhatikan tingkat kebutuhan atau kekayaan. Namun politik ekonomi Islam bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer setiap individu, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan, serta terpenuhinya kebutuhan sekunder sebesar kadar kemampuan masing-masing individu. Maka, dasar ekonomi Islam adalah pendistribusian kekayaan, dengan mengatur cara penguasaan kekayaan dari sumbernya, yang kemudian diharapkan darinya akan muncul pertumbuhan ekonomi. Dan permasalahan distribusi ini telah diatur oleh hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan masalah kepemilikan, perolehan harta, pengelolaan harta, pengembangan harta, mata uang, jual beli dan distribusi kekayaan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman dalam Al Quran surat Al Hasyr ayat 7 : “…supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu.” Kehebatan sistem ekonomi ini telah dibuktikan oleh generasi-generasi Islam terdahulu. Wallahu a’lamu bishowab. *** - (Finalis Lomba Esai Ilmiah Harun Yahya Internasional Representative Indonesia)
Dekorporatokrasi dan Swakelola Sumber Daya Tambang Demi Keberlanjutan Hidup Manusia dan Ekologi
Thaksin Shinawatra, Perdana Menteri Thailand, didesak mundur dari kursi kekuasaannya oleh para demonstran—(hanya) gara-gara menjual perusahaan telekomunikasi (milik keluarga sendiri!) Shin Corporation kepada perusahaan asing Temasek Holdings, yang notabene adalah perusahaan dari tetangga seberang pintu, Singapura. Orang Thai marah dan tersinggung karena Shin Corp sudah dianggap sebagai aset nasional. Di republik kita nan gagah perkasa ini, banyak aset negara, milik swasta, maupun pribadi, yang dijual ke tangan asing (dengan harga murah!) dengan berbagai dalih yang patriotik “demi kepentingan rakyat dan negara”. Yang sekarang sedang hangat diperjualbelikan dan seperti dirayakan sebagai “kemenangan” adalah keunggulan bumi Indonesia dengan sebutan Blok Cepu dan perut bumi Papua yang dihamili oleh PT Freeport Indonesia, penguasaan (atau penjualan?) pulau-pulau dan hutan belantara, laut dan udara Nusantara yang dulu pada tahun 1945 telah berhasil dikuasai kembali oleh anak negeri: “Bumi, laut dan udara dengan segenap kandungan kekayaannya, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Begitu kira-kira kredo semangat undang-undang aslinya. Dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Benarkah? Siapa jual, siapa untung, siapa rugi, siapa merampas, siapa kehilangan? (Kompas, 19/3/2006)
Sebutlah sebait solilokui alias senandika yang ditelorkan Suka Hardjana dalam rubrik Asal Usul Kompas Minggu, yang keluar dari tsunami tanda tanya tentang apa yang telah terjadi di negeri seribu pulau ini. Sebuah pangudarasa yang dikatakan Suka Hardjana menjustifikasi kebenaran pepatah lama – lain lubuk lain ikannya, lain ladang lain belalang. Kemudian diakhirinya dengan pertanyaan besar (atau pernyataan?). Apakah kredo para founding fathers republik ini tidak lagi diwarisi oleh para anak cucunya? Apakah kredo itu telah tergadai pula?
Indonesia: Negara atau Paguyuban?
 Itulah, pertanyaan yang lazim teracungkan atas berbagai kebijakan yang tidak bijak di republik ini. Ketika bangsa yang memiliki ikon guyub rukun, berubah menjadi pelakon dalam kebrutalan, pertikaian, perselisihan, bentrokan massal dan baku bunuh. Sebuah lakon dalam pagelaran yang dimainkan dengan wicara dan sabetan yang luar biasa lihai oleh Ki Dalang Penjajah Asing, dengan wayang-wayang yang terlihat telanjang. Ada kembul bojana Senapati Kuda Laut yang telah menyerahkan Kurusetra Cepu kepada Raja Raksasa Patra Exxon. Ada perang tanding antara para punggawa dan para kawula yang mengakibatkan tewasnya 5 punggawa, disaksikan oleh Buto Emas Freeport dengan terbahak-bahak. Sang Raja, Patih, Adipati seluruhnya telah menjadi wayang-wayang yang hanya bisa mobat-mabit kesana-kemari dimainkan Sang Dalang. Sebuah lakon Goro-goro yang teramat layak meraih Academy Award.
Itulah, pertanyaan yang lazim teracungkan atas berbagai kebijakan yang tidak bijak di republik ini. Ketika bangsa yang memiliki ikon guyub rukun, berubah menjadi pelakon dalam kebrutalan, pertikaian, perselisihan, bentrokan massal dan baku bunuh. Sebuah lakon dalam pagelaran yang dimainkan dengan wicara dan sabetan yang luar biasa lihai oleh Ki Dalang Penjajah Asing, dengan wayang-wayang yang terlihat telanjang. Ada kembul bojana Senapati Kuda Laut yang telah menyerahkan Kurusetra Cepu kepada Raja Raksasa Patra Exxon. Ada perang tanding antara para punggawa dan para kawula yang mengakibatkan tewasnya 5 punggawa, disaksikan oleh Buto Emas Freeport dengan terbahak-bahak. Sang Raja, Patih, Adipati seluruhnya telah menjadi wayang-wayang yang hanya bisa mobat-mabit kesana-kemari dimainkan Sang Dalang. Sebuah lakon Goro-goro yang teramat layak meraih Academy Award.
Jadi, apakah Indonesia adalah sekedar pagelaran wayang? Kita harap tidak. Kalau begitu apakah Indonesia sebuah paguyuban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paguyuban adalah perkumpulan yang didirikan orang-orang yang sepaham untuk membina persatuan dan kerukunan diantara para anggotanya. Jika kita melihat adanya perangkat-perang perundang-undangan, struktur pemerintahan dan tata relasi kewarganegaraan, sepertinya Indonesia bukan sekedar paguyuban. Lantas, apakah Indonesia adalah sebuah negara? Entah, jawabannya bisa bukan negara atau negara yang bukan-bukan.
Roger H. Soltau menyatakan bahwa negara adalah an agency or authority managing or controlling these common affairs on behalf of and in the name of the community—dengan mengatasnamakan masyarakat, negara menjadi alat dan wewenang dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama. Kemudian menyangkut fungsi negara, Charles E. Merriam menyebutkan setidaknya lima fungsi, 1) keamanan ekstern, 2) ketertiban intern, 3) keadilan, 4) kesejahteraan umum, dan 5) kebebasan.
Lebih khusus dalam bidang perekonomian, Irawan (Republika, 29/3/2006) menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga fungsi negara yang diketahui secara umum oleh para ekonom, yaitu fungsi alokatif, fungsi distributif, dan fungsi stabilitatif. Fungsi alokatif yaitu negara mengalokasikan anggarannya dengan tujuan menyediakan secara memadai barang-barang publik kepada masyarakat. Barang-barang publik ini diserahkan kepada negara penyediaannya karena sangat dibutuhkan publik. Fungsi distributif ditujukan untuk menolong kelompok-kelompok masyarakat yang terpaksa terpinggirkan dan termajinalisasi dalam interaksi ekonomi melalui mekanisme pasar. Sedangkan melalui fungsi stabilitatif, negara mencoba melakukan tindakan-tindakan antisipasi terhadap instabilitas ekonomi. Maka, sebenarnya negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (bonum publicum).
Jadi, sebuah negarakah Indonesia? Sepertinya…, ya! Tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah: “Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Jadi, sebuah isyarat bonum publicum?
Akan tetapi, semua orang juga tahu, kini Indonesia menjadi negara miskin. Pendapatan kotor nasional (GNP) perkapitanya hanya sedikit lebih besar dari Zimbabme, sebuah negara miskin di Afrika. Kekayaan Indonesia lebih banyak tergadai ke pihak asing, seperti minyak hampir 90% didominasi pihak asing. Emas di Freeport, Indosat, BCA, Danamon, sebagian Perkebunan, juga tergadai ke pihak asing. Utang negara luar biasa besar, lebih dari Rp 1.200-an triliun. Pertanyaannya, siapa yang harus menanggung beban utang yang demikian besar itu ? Tidak lain, tentu saja adalah rakyat Indonesia sendiri. Hal ini tampak pada pos penerimaan dalam APBN dari sektor pajak yang mencapai sekitar 70 persen.
Maka tampaknya, kebahagiaan itu masih sekedar isyarat. Survei Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2005 menunjukkan penduduk Indonesia dengan pendapatan 120 ribu/orang/bulan sebanyak 4,7 juta kepala keluarga/KK (16 juta jiwa), pendapatan 150 ribu/orang/bulan sebanyak 10 juta KK (40 juta jiwa) dan pendapatan 175 ribu/orang/bulan sebanyak 15,5 juta KK (62 juta jiwa). Sementara itu angka pengangguran pada Oktober 2005, masih menurut BPS sebanyak 11,6 juta jiwa.
Ironinya, pada bulan Oktober 2005 pula pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM rata-rata 108 persen. Masih untung TDL yang rencananya bakal naik 15 persen, batal dinaikkan tahun ini, entah tahun depan. Tentu, kenaikan-kenaikan itu tentu akan menambah angka-angka itu. BPS saja menyatakan, kenaikan BBM 35 persen, akan membuat angka kemiskinan baru sekitar 20 juta orang.
Kondisi demikian, akhirnya memunculkan bola salju permasalahan. Hasil Susenas 2003 menyebutkan bahwa sekitar 27,3 persen balita Indonesia kekuragan gizi. Artinya, dari jumlah 18 juta balita pada tahun 2003, 4,9 juta mengalami masalah gizi buruk. Tahun 2005, sesuai proyeksi penduduk Indonesia oleh BPS, anak usia 1-4 tahun adalah sebanyak 20,87 juta. Jika angka 27,3 persen digunakan, maka diperkirakan 5,7 juta anak balita akan mengalami masalah gizi buruk. Kemudian, sebanyak 8 persen, atau 1,67 juta balita mengalami busung lapar atau kekurangan gizi yang amat parah.
Sementara itu, perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar (basic need) menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan juga sangat rendah. Hal ini tercermin dari neraca APBN 2005, dimana hanya 5,82 persen anggaran dialokasikan untuk pendidikan dan 1,54 persen untuk bidang kesehatan. Sementara agenda privatisasi pendidikan mengemuka, kasus endemi penyakit-penyakit terus meluas.
Jadi, bagaimana dengan bonum publicum? Jangan-jangan kedepan Indonesia masuk dalam kategori ketiga atau keempat dalam kategorisasi negara-bangsa (nation-state) menurut Stoddar, yaitu: 1) kuat (powerfulstate), 2) lemah (weakstate), 3) gagal (failedstate), dan 4) runtuh (collapsedstate).
“Menggali” Pertambangan Indonesia
Salah satu sektor yang potensial mendatangkan pemasukan bagi negara adalah mengambil sumberdaya dari alam. Dan diantara sumberdaya alam (SDA) yang paling berpengaruh adalah sumberdaya mineral dan energi yang penyebarannya meluas dari Sabang sampai Merauke, baik yang terletak di darat maupun di daerah lepas pantai. Selain endapan batubara, minyak bumi dan gas alam, sumberdaya mineral tersebut merupakan bahan galian logam, bahan galian industri dan bahan bangunan. Sebagian dari bahan galian mineral logam seperti emas, perak, timah, nikel, tembaga dan sebagainya telah ditambang, tetapi masih banyak potensi yang belum dieksploitasi, bahkan belum diselidiki atau dieksplorasi.
Subandoro (2001) menyebutkan, secara umum penyebaran bahan galian logam terdapat didaerah pegunungan karena berkaitan dengan kegiatan intrusi dan ekstrusi magma di daerah-daerah pegunungan yang terangkat karena gerakan tektonik akibat benturan antara Lempeng Benua. Misalnya, penyebaran mineral logam di sepanjang Pegunungan Bukit Barisan di Sumatra, Pegunungan Selatan Pulau Jawa-Nusatenggara, Pegunungan Meratus di Kalimantan, Pegunungan yang memanjang dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah sampai Sulawesi Utara, Pegunungan di Kepulauan Maluku, dan Pegunungan di Irian Jaya. Deretan pegunungan-pegunungan tersebut terbentuk karena terjadinya benturan antara Lempeng Benua. Lempeng yang merupakan dasar Samudra Hindia bergerak kearah utara sehingga membentur Paparan Sunda yang stabil. Akibatnya, terjadilah pengangkatan daratan yang membentuk pegunungan di daerah Sumatra dan Jawa. Di wilayah Indonesia bagian timur terjadi benturan antara tiga lempeng benua, yaitu antara Lempeng Samudra Pasifik, Lempeng Benua Australia dan Paparan Sunda.
Potensi yang sedemikian besar ini digambarkan oleh Survei Industri Pertambangan Indonesia 2002 yang dipublikasikan pada November 2002 oleh PricewaterhouseCoopers, bahwa industri pertambangan Indonesia memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan kinerja indutri pertambangan yang menyetorkan:
a. Kontribusi total pada ekonomi Indonesia: 11.777,8 milyar rupiah (1999), 13.540,4 milyar rupiah (2000), 14.309,4 milyar rupiah (2001).
b. Kontribusi industri tambang pada GDP: 31.208,5 milyar rupiah (1999), 34.031,6 milyar rupiah (2000), 45.558,1 milyar rupiah (2001).
c. Pendapatan total pemerintah: 6.651,6 milyar rupiah (1999), 6.762,8 milyar rupiah (2000), 8.329,8 milyar rupiah (2001).
d. Total pajak perusahaan (termasuk royalti dan pajak tidak langsung): 478,2 juta US$ (1999), 571,9 juta US$ (2000), 577,1 juta US$ (2001), pada 2001 melambangkan total kurs pajak 60.1%.
e. Pembangunan masyarakat dan daerah: 211,0 milyar rupiah (1999), 269,7 milyar rupiah (2000), 279,1 milyar rupiah (2001).
f. Jumlah tenaga kerja langsung Indonesia: lebih dari 36.887 (1999), 32.189 (2000) dan 32.909 (2001), mewakili 98% dari total angkatan kerja.
g. Pelatihan tenaga kerja: 118,6 milyar rupiah (1999), 134,6 milyar rupiah (2000), 108,5 milyar rupiah (2001).
Sungguh suatu kontribusi yang lumayan besar bagi pengelolaan negara. Namun harus disadari bahwa sumberdaya mineral dan energi merupakan sumber daya alam yang tak terbaharui atau non-renewable resource, artinya sekali bahan galian ini dikeruk, maka tidak akan dapat pulih atau kembali ke keadaan semula. Oleh karenanya, pemanfaatan sumberdaya mineral ini haruslah dilakukan secara bijaksana dan haruslah dipandang sebagai aset alam sehingga pengelolaannya pun harus juga mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang.
 Misalnya tambang di bumi Papua saja, adalah potensi SDA yang luar biasa besar. Jika saja SDA itu dikelola dan dimanfaatkan secara optimal oleh negeri ini, niscaya ia akan bisa menyelesaikan berbagai problem ekonomi yang tersebut diatas yang sedang melilit negeri ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri BUMN, akibat pemblokiran Freeport oleh penduduk setempat beberapa saat lalu, Pemerintah Indonesia rugi 2,7 triliun setiap hari. Padahal kita tahu bahwa nilai tersebut baru dari 9% royalti dan sedikit pajak. Menurut Econit, royalti yang diberikan Freeport ke pemerintah tidak berubah, hanya 1-3,5 persen sehingga penerimaan pemerintah dari pajak, royalti, dan dividen FI hanya 479 juta dolar AS. Jumlah itu tentu masih sangat jauh dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh Freeport sekitar 1,5 miliar dolar AS (tahun 1996), yang dipotong 1 persen untuk dana pengembangan masyarakat Papua yang ketika itu sekitar 15 juta dolar AS (Gatra, 10/1998).
Misalnya tambang di bumi Papua saja, adalah potensi SDA yang luar biasa besar. Jika saja SDA itu dikelola dan dimanfaatkan secara optimal oleh negeri ini, niscaya ia akan bisa menyelesaikan berbagai problem ekonomi yang tersebut diatas yang sedang melilit negeri ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri BUMN, akibat pemblokiran Freeport oleh penduduk setempat beberapa saat lalu, Pemerintah Indonesia rugi 2,7 triliun setiap hari. Padahal kita tahu bahwa nilai tersebut baru dari 9% royalti dan sedikit pajak. Menurut Econit, royalti yang diberikan Freeport ke pemerintah tidak berubah, hanya 1-3,5 persen sehingga penerimaan pemerintah dari pajak, royalti, dan dividen FI hanya 479 juta dolar AS. Jumlah itu tentu masih sangat jauh dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh Freeport sekitar 1,5 miliar dolar AS (tahun 1996), yang dipotong 1 persen untuk dana pengembangan masyarakat Papua yang ketika itu sekitar 15 juta dolar AS (Gatra, 10/1998).
Bagaimana jika kita tidak hanya mendapatkan royalti dan pajaknya saja, tetapi juga keuntungan/laba secara penuh. Jelas, Pemerintah Indonesia akan mendapatkan dana segar minimal Rp 73,71 trilun perbulannya atau setara dengan Rp 884,52 triliun pertahun. Sungguh, angka ini cukup untuk memberikan subsidi kepada rakyat sehingga BBM tidak perlu naik (Rp 10,5 triliun). Jika BBM tidak naik, maka TDL pun tidak akan pernah naik. Uang itu juga bisa digunakan untuk menutupi defisit APBN Rp 198 triliun), juga bisa digunakan untuk membayar utang (pokok dan bunganya sebesar Rp 159,7 triliun). Sisanya bisa digunakan untuk membiayai pendidikan gratis, biaya kesehatan murah, dan perumahan bagi rakyat.
Lainnya, misalnya blok Cepu yang berdasarkan hasil survei dan kajian (technical evaluation study/TEA) Humpuss Patragas tahun 1992-1995, cadangan minyaknya mencapai 10,9 miliar barel dan sebanyak 2,6 miliar barel yang dapat dieksplorasi dalam bentuk minyak. Maka blok Cepu mengandung cadangan minyak terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Cadangan minyak di Indonesia secara keseluruhan, selama ini diperkirakan hanya sekitar 9,7 miliar barel.
Sungguh, tambang di bumi Papua, Cepu dan dibanyak tempat lainnya, adalah salah satu aset bangsa yang sangat strategis dan mampu dijadikan penopang bagi pelayanan masyarakat secara berkeadilan dan menyejahterakan. Namun, itu semua hanya menjadi fatamorgana jika dikelola oleh asing, bukan oleh bangsa sendiri, apalagi dilakukan secara eksploitatif dan dalam skala yang massif.
Walhi (2004) mencatat, tidak kurang dari 30% wilayah daratan Indonesia sudah dialokasikan bagi operasi pertambangan, yang meliputi baik pertambangan mineral, batubara maupun pertambangan galian C. Tidak jarang wilayah-wilayah konsesi pertambangan tersebut tumpang tindih dengan wilayah hutan yang kaya dengan keanekaragaman hayati dan juga wilayah-wilayah hidup masyarakat adat.
Menurut Walhi, operasi pertambangan yang dilakukan di Indonesia seringkali menimbulkan berbagai dampak negatif, baik terhadap lingkungan hidup, kehidupan sosial, ekonomi, budaya masyarakat adat maupun budaya masyarakat lokal. Beberapa dampak negatif aktivitas pertambangan antara lain:
a. Pertambangan Menciptakan Bencana Lingkungan
Di seluruh Indonesia, operasi pertambangan menciptakan kehancuran dan pencemaran lingkungan. Ongkos produksi rendah yang dibangga-banggakan perusahaan dalam laporan tahunannya dicapai dengan mengorbankan lingkungan. Sebagian besar operasi pertambangan dilakukan secara terbuka (open pit) di mana ketika suatu wilayah sudah dibuka untuk pertambangan, maka kerusakan yang terjadi di wilayah tersebut tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible damage). Selain itu, hampir semua operasi pertambangan melakukan pembuangan limbah secara langsung ke sungai, lembah, dan laut. Hal ini mengakibatkan perusakan dan pencemaran sungai dan laut yang merupakan sumber kehidupan masyarakat setempat.
b. Pertambangan Menghancurkan Sumber-Sumber Kehidupan Masyarakat
Wilayah operasi pertambangan yang seringkali tumpang tindih dengan wilayah hutan serta wilayah hidup masyarakat adat dan lokal telah menimbulkan konflik atas hak kelola dan hak kuasa masyarakat setempat. Tidak adanya pengakuan pemerintah terhadap hak-hak masyarakat adat atas wilayah hidup mereka menyebabkan pemberian wilayah konsesi dengan semena-mena tanpa ada persetujuan dari masyarakat. Kelompok masyarakat harus terusir dan kehilangan sumber-sumber kehidupannya, baik akibat tanah yang dirampas mapun akibat tercemar dan rusaknya lingkungan akibat limbah operasi pertambangan.
c. Pertambangan Memicu Kekerasan dan Ketidakadilan terhadap Perempuan
Perempuan adalah kelompok yang paling rentan di dalam komunitas yang akan memikul dampak terbesar dari operasi pertambangan. Dalam banyak kasus, perempuan telah menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual dari personel perusahaan, maupun kekerasan oleh aparat keamanan dan personel perusahaan. Sebagian dari dampak terhadap perekonomian setempat adalah bahwa perempuan seringkali dijauhkan dari sumber penghidupannya semula. Hal ini dalam banyak kasus memaksa mereka untuk terlibat dalam prostitusi.
d. Pertambangan Meningkatkan Pelanggaran HAM dan Militerisme
Di banyak operasi pertambangan di seluruh Indonesia, aparat keamanan dan militer seringkali menjadi pendukung pengamanan operasi pertambangan. Ketika perusahaan pertambangan pertama kali datang ke suatu lokasi, sering terjadi pengusiran-pengusiran dan kekerasan terhadap warga masyarakat setempat. Di dalam UU Pertambangan No. 11 tahun 1967, operasi pertambangan dikategorikan sebagai proyek vital dan strategis. Hal ini menjadi pembenaran bagi dilakukannya pengamanan, baik oleh tentara maupun aparat keamanan lainnya. Dalam banyak kasus, perusahaan-perusahaan pertambangan multinasional juga melakukan pembayaran terhadap aparat keamanan dengan tujuan untuk menjaga keamanan perusahaan.
Detail tentang dampak-dampak negatif tersebut misalnya bisa dilihat dari kasus Freeport. Sejak bulan April tahun 1967 Freeport telah memulai kegiatan eksplorasinya di Papua—yang diperkirakan mengandung cadangan bijih emas terbesar di dunia—sebanyak 2,5 miliar ton melalui Kontrak Karya I yang penuh dengan intrik dan tipudaya. Kegiatan eksplorasinya pun tak tanggung-tanggung. Sepanjang tahun 1998, misalnya, PT Freeport Indonesia menghasilkan agregat penjualan 1,71 miliar pon tembaga dan 2,77 juta ons emas (Sabili, 16/02/2006). Menurut Catatan Departemen Energi dan Sumber Daya Alam, pada tahun 1992 hingga 2002 Freeport memproduksi 5,5 juta ton tembaga, 828 ton perak dan 533 ton emas. Dengan penghasilan itu Freeport mengantongi keuntungan triliunan rupiah sepanjang tahun.
Wajar jika hanya dalam kurun waktu dua tahun berproduksi (tahun 1973), Freeport yang dulunya perusahaan tambang kecil berhasil mengantongi perolehan bersih US$ 60 juta dari tembaga yang ditambangnya itu. Itu belum termasuk hasil tambang ikutannya seperti emas, perak, dan yang lainnya. Itu juga belum ditambah penemuan lokasi tambang baru (tahun 1988) di Pegunungan Grasberg yang mempunyai timbunan emas, perak, dan tembaga senilai US$ 60 juta miliar. Walhasil, sejak awal Freeport telah mengeruk dengan serakah kekayaan sumberdaya alam Papua pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.
Pada zaman reformasi nasib PT Freeport Indonesia semakin bersinar. Pada tahun 2001, laba bersih yang dibukukan perusahaan ini mencapai US$ 304,2 juta. Pada tahun 2002 naik menjadi US$ 398,5 juta. Tahun berikutnya, 2003 laba bersihnya melonjak hingga US$ 484,9 juta. Yang mengherankan, dari laba bersih sebesar itu, sesungguhnya yang dibagikan sebagai deviden hanya 15%-nya saja. Padahal Pemerintah sampai saat ini hanya memiliki saham sebanyak 9,36%, sedangkan PT Freeport menguasai 90,64% (Kontan, 6/9/2004).
Kemudian, masalah pencemaran lingkungan juga menjadi persoalan yang serius. Penambangan oleh Freeport telah menghasilkan galian berupa potential acid drainage (air asam tambang) dan limbah tailing (butiran pasir alami yang halus hasil pengolahan konsentrat). Sehari-hari Freeport memproduksi tidak kurang dari 250 ribu metrik ton bahan tambang. Material bahan yang diambil hanya 3%-nya. Inilah yang diolah menjadi konsentrat yang kemudian diangkut ke luar negeri melalui pipa yang dipasang ke kapal pengangkut di Laut Arafuru. Sisanya, sebanyak 97% berbentuk tailing. Akibatnya, sungai-sungai di sana tidak lagi disebut sungai karena berwarna coklat lumpur tempat pembuangan limbah tailing. Limbah Freeport juga telah menghancurkan vegetasi hutan daratan di wilayah Timika. Selain itu, Danau Wanagon pernah jebol dan menelan korban jiwa karena kelebihan kapasitas pembuangan dan terjadinya perubahan iklim mikro akibat penambangan terbuka.
Sebuah lembaga audit lingkungan independen Dames & Moore melaporkan pada tahun 1996—dan disetujui oleh pihak Freeport—bahwa ada sekitar 3,2 miliar ton limbah yang bakal dihasilkan tambang tersebut selama beroperasinya. Faktanya, telah terjadi pencemaran dan lingkungan baik hutan, danau dan sungai maupun kawasan tropis seluas 11 mil persegi.
Dampak sosial dari keberadaan Freeport juga tidak bisa dipandang remeh. Berlimpahnya dana yang beredar di sana justru melahirkan bisnis prostitusi. Ironisnya, dari tahun ke tahun, bisnis esek-esek ini cenderung meningkat. Silitonga (2002) menyebutkan bahwa propinsi Papua menduduki peringkat teratas penderita HIV/AIDS di Indonesia, dan dalam interaksi kota-kota dengan penyebaran tertinggi seperti Merauke, Sorong dan Jayapura, menempatkan masyarakat Timika dalam daftar paling beresiko terkena HIV/AIDS. Silitonga merilis ulang data yang dipublikasikan oleh Subdin BPP dan PL Dinas Kesehatan Propinsi Papua bahwa pada akhir Desember 2001 dilaporkan sebayak 718 kasus HIV/AIDS di propinsi Papua, dan 164 kasus diantaranya ditemukan di Timika. Di Timika sendiri, tempat beroperasinya PT Freeport Indonesia yang mempekerjakan sekitar 12,000 pekerja laki-laki, diidentifikasikan dari 164 kasus HIV/AIDS tersebut, 73 persen penderitanya adalah penduduk Papua sendiri, dimana 60 persen dari jumlah itu adalah perempuan Papua. Jumlah ini cenderung semakin meningkat.
Semua hal tersebut terjadi jelas karena pengelolaan pertambangan di Indonesia menggunakan paradigma dan cara-cara kapitalistik dan imperialistik, yang hanya mementingkan golongan kapitalis tertentu dan segelintir pejabat saja.
Richardson misalnya dalam International Herald Tribune (3/4/2000) menyebutkan bahwa 81,28 persen saham Freeport dimiliki oleh Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. Pemerintah Indonesia hanya memiliki 9,36 persen saham, sebagaimana PT Indocopper Investama Corp. 49 saham Indocopper dimiliki oleh Freeport-McMoran dan 50,48 persen dimiliki oleh Nusamba Mineral Industries, perusahaan yang memiliki hubungan dengan Suharto sebagai penguasa Orde Baru. The New York Times (27/12/2005) memaparkan bahwa anggota TNI dan Polri secara resmi dibayar oleh Freeport. Sementara itu, Blok Cepu yang kini akhirnya jatuh kedalam pelukan Exxon Mobil, sebelumnya dikuasai oleh Humpuss Patragas yang merupakan bisnis keluarga Cendana. Dalam skala lebih kecil, belakangan muncul pengusaha-pengusaha swasta nasional yang ikut terjun dalam bisnis minyak bumi seperti Arifin Panigoro dengan Medco-nya, Ibrahim Risjad, Srikandi Hakim, dan Astra International (SWA, April-Mei 1996).
Jadi, wajar jika kemudian Suka Hardjana bertanya, “Siapa jual, siapa untung, siapa rugi, siapa merampas, siapa kehilangan?“
Dekorporatokrasi dan Swakelola Pertambangan
Korporatokrasi atau kadang disebut korporokrasi adalah neologisme atau bentukan baru untuk menggambarkan sebuah pemerintah yang tunduk dibawah tekanan korporasi. Terkadang korporatokrasi dihubungkan dengan plutokrasi, pemerintahan oleh pemilik kekayaan (the have).
Dalam korporatokrasi, ketika seseorang secara prinsip menjadi shareholder dalam sebuah korporasi, dalam kenyataannya hanya yang kuat yang dapat memberikan pengaruh pada pengambilan keputusan dan akhirnya pada seluruh aktivitas korporasi. Dalam kasus kenegaraan, korporatokrasi akan muncul ketika pemerintah ‘melegalkan’ politik uang yang terjadi diantara para politikus. Sehingga para politikus di eksekutif maupun di legislatif akan sangat corporate-friendly, dan sangat membantu korporasi memain-mainkan hukum sesuai keinginan dan kebutuhan mereka. Hal ini kiranya yang terjadi pada kasus Freeport, dimana tampak jelas bahwa justru UU Pertambangan No. 11 tahun 1967 dibuat untuk ‘memanjakan’ Freeport yang beroperasi di Papua beberapa waktu sebelum UU tersebut dibuat dan disahkan oleh penguasa Orde Baru, Suharto.
Lebih jauh, bahkan dalam kampanye untuk menjadi penguasa negara atau daerah, para politikus didukung oleh para pengusaha untuk biaya kampanyenya. Konsekuensinya, ketika si politikus berhasil suara rakyat, maka kepentingan korporasi akan mendominasi kebijakannya. Bahkan, dalam kasus yang lebih jahat, para politikus itu pulalah yang menjadi pengelola korporasi, dan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya akan mengikuti kaidah ekonomi kapitalis yang hanya menguntungkan korporasinya.
John Perkins dalam bukunya yang terkenal Confessions of an Economic Hit Man (2004) mendeskripsikan korporatokrasi sebagai pemerintahan yang dikendalikan oleh “perusahaan besar, bank internasional dan pemerintah”. Perkins melihat korporatokrasi menjelma dalam siklus seperti berikut: Bank Dunia mengeluarkan bantuan untuk membangun bangsa-bangsa khususnya untuk membayar proyek-proyek pembangunan berskala besar; kontrak-kontrak kemudian disetujui dengan memakai perusahaan-perusahaan Amerika; dan hasilnya, negara-negara resipien tersebut menjadi terjerat dalam jaring bunga dan pokok utang yang tidak dapat mereka bayar. Korporasi-korporasi Amerika terus meningkatkan keuntungan korporasinya, dan pemerintah AS mendapatkan keuntungan terus dengan mengamankan operasi korporasi melalui kontrol dan kekuatan politik pada negara-negara berkembang dengan kepemilikan SDA yang besar. Dan akhirnya, Perkins menegaskan bahwa mayoritas penduduk di negara-negara berkembang ini tidak akan menikmati keuntungan yang ada, bahkan bagian terbesar dari anggaran negara lebih dialokasikan untuk mengatasi utang negara daripada untuk memberikan kesejahteraan pada rakyatnya. Indonesia adalah contoh yang tepat dalam pembuktian tesis Perkins ini.
 Kemudian, Perkins menggambarkan bagaimana harmoni antara korporasi besar, bank internasional dan pemerintah yang menurutnya sebagai ‘Tiga Pilar Korporatokrasi’, memberikan kemudahan bagi elite untuk bergerak pada sektor ini. Perkins mencontohkan sepak terjang Halliburton yang dikomandani oleh Wapres AS Dick Cheney. Begitu pula kepentingan keluarga Bush dan Condoleeza Rice dalam pengerukan SDA di Iraq dan Afghanistan. Bisnis minyak sangat mewarnai kebijakan pemerintah Amerika Serikat. Penyerangan terhadap Afghanistan yang berdalih penyerbuan terhadap sarang teroris adalah karena minyak. Begitu juga invasi ke Irak, semata-mata karena Amerika ingin menguasai minyak di negara tersebut.
Kemudian, Perkins menggambarkan bagaimana harmoni antara korporasi besar, bank internasional dan pemerintah yang menurutnya sebagai ‘Tiga Pilar Korporatokrasi’, memberikan kemudahan bagi elite untuk bergerak pada sektor ini. Perkins mencontohkan sepak terjang Halliburton yang dikomandani oleh Wapres AS Dick Cheney. Begitu pula kepentingan keluarga Bush dan Condoleeza Rice dalam pengerukan SDA di Iraq dan Afghanistan. Bisnis minyak sangat mewarnai kebijakan pemerintah Amerika Serikat. Penyerangan terhadap Afghanistan yang berdalih penyerbuan terhadap sarang teroris adalah karena minyak. Begitu juga invasi ke Irak, semata-mata karena Amerika ingin menguasai minyak di negara tersebut.
Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Putusan bahwa Exxon yang menjadi pengelola adalah putusan bisnis, tapi keputusan bisnis yang dilandasi kepentingan politis. Pemerintah Amerika sangat berperan dalam menentukan keputusan tersebut. Sebagai ‘orang minyak’, Bush tahu betul bahwa Exxon sangat berkepentingan mengelola Cepu. Lagi pula, ini balas budi Bush terhadap perusahaan itu. Maklum, Exxon yang berhasil memupuk keuntungan 36,2 miliar dolar AS pada 2005, sudah menyumbang 2,8 juta dolar AS kepada Bush dalam pemilu presiden 2004 silam. Belum terhitung sumbangan-sumbangan lain terhadap orang-orang di sekitar Bush.
Ulasan Perkins ini cukup membuat gerah pemerintah Amerika. Melalui U.S. National Security Agency (NSA), pemerintah Amerika membantah tuduhan Perkins dengan argumen bahwa pemerintah AS baru-baru ini telah berinisiatif untuk menghapus utang banyak negara-negara miskin–heavily indebted poor countries (HIPC). Misalnya pada tahun 2004, Bush berkehendak untuk menghapus utang negara-negara termiskin di dunia. Setahun kemudian, pada konferensi para pemimpin Kelompok Delapan (G8) di Gleneagles pada Juli 2005, menyepakati untuk menghapus 18 negara miskin, dan mengabaikan 17 juta dollar US utang Nigeria, sebagai penghapusan utang terbesar yang pernah terjadi. Pada September 2005, Timothy Adams, Sekretaris untuk Hubungan Internasional pada Departemen Keuangan AS menjelaskan, “Dibawah program ini, 18 negara termiskin dunia akan dihapuskan utang-utangnya, meliputi: Benin, Bolivia, Burkina Faso, Ethiopia, Ghana, Guyana, Honduras, Madagaskar, Mali, Mauritania, Mozambik, Nikaragua, Niger, Rwanda, Senegal, Tanzania, Uganda, dan Zambia. Total utang yang dihapus itu hingga mencapai 60 juta dollar AS ketika proses penghapusan itu selesai.”
Walaupun ulasan Perkins ini dibantah dan bantahan itu terkesan elegan, namun jangan lupa bahwa penghapusan itu dilakukan setelah kurang lebih 60 tahun mereka memeras penduduk di negara-negara berkembang dan merampok kekayaan SDA-nya. Gambaran Freeport yang telah merubah gunung emas menjadi lembah adalah bukti kerakusan para negara kapitalis tersebut. Belum lagi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara-negara yang masuk dalam skema penghapusan utang itu. Dominasi politik dan ekonomi oleh AS dan para kompradornya akan terus menghantui negara-negara yang terperangkap dalam utang-utang internasional.
Sebuah kajian industri ekstraktif— EIR (Extractive Industries Review), pada ulang tahun Bank Dunia ke-60, 22 Juli 2004, meminta Bank Dunia untuk mengakhiri pendanaan bagi proyek pertambangan minyak dan tambang. Jika Bank Dunia terus melanjutkan kebijakan ini, berarti Bank Dunia tetap meletakkan profit bagi korporasi di atas rakyat dan planet. Artinya ulang tahun ke-60 Bank Dunia ini, tidak hanya menandai 60 tahun kegagalan kebijakan, 60 tahun penyalahgunaan hutang, 60 tahun peningkatan hutang dan 60 tahun proyek-proyek pembangunan Bank Dunia yang meragukan dan mengorbankan lingkungan, perempuan, masyarakat adat dan kelompok marginal lain di seluruh dunia, tapi juga sebagai titik lanjut penghancuran dunia.
EIR antara lain menuntut agar Bank Dunia:
1. Mendapatkan Prior Informed Consent (persetujuan tanpa paksa) dari masyarakat lokal dan masyarakat adat yang akan terkena dampak projek sebagai suatu syarat pendanaan;
2. Mengurangi secara bertahap hingga berhenti mendanai batubara (sekarang) dan minyak (pada tahun 2008); dan menggunakan sumberdayanya yang terbatas untuk meningkatkan pendanaannya untuk energi terbarukan 20% per tahun;
3. Menghormati hak masyarakat adat atas tanah adat sebagai prekondisi pendanaan;
4. Memastikan bahwa hasil dari proyek yang didanai oleh Bank Dunia juga bermanfaat untuk semua masyarakat lokal dimana proyek dilaksanan;
5. Menjamin hak-hak buruh sebagaimana telah dijamin oleh ILO;
6. Meminta Bank Dunia untuk tidak mendanai proyek yang menggunakan metode Submarine Tailing Disposal sampai dibuktikan tidak berbahaya;
7. Meningkatkan transparansi keuangan, dan transparansi proyek secara umum kepada publik; dan
8. Segera melakukan berbagai reformasi yang diperlukan dalam tubuh Bank Dunia untuk memungkinkan terlaksananya rekomendasi-rekomendasi yang lain, ini sangat penting mengingat hingga kini tekanan untuk ‘segera memberi pinjaman’ dialami oleh banyak staf Bank Dunia sehingga berakibat melemahnya kebijakan perlindungan sosial dan lingkungan dalam proyek-proyek Bank Dunia.
EIR menyimpulkan bahwa jika Bank Dunia ingin memenuhi mandatnya untuk mencapai pengentasan kemiskinan, maka seharusnya hanya mendukung industri ekstraktif jika sejumlah kondisi ‘good governance’ dan kondisi yang positif lainnya sudah ada. Lebih lanjut EIR menyatakan bahwa jika ingin menyumbang kepada pembangunan berkelanjutan secara lebih efektif, maka sebaiknya Bank Dunia menjadikan dirinya pendukung utama bagi energi terbarukan, daripada terus mendanai pertambangan batu bara dan minyak. Bank Dunia disarankan untuk merealokasikan dana-dananya dan secara agresif meningkatkan portfolio proyek-proyek energi terbarukan sebesar 20% pertahun, hingga pada akhirnya di tahun 2008 nanti portfolio energi Bank Dunia didominasi oleh proyek-proyek energi terbarukan. Pertanyaannya kemudian, akankah Bank Dunia memenuhi rekomendasi itu, jika peranan dan dominasi negara-negara kapitalis masih sangat mengakar dalam tubuh Bank Dunia??
Tidak hanya Bank Dunia, permainan bola ekonomi dunia juga dimainkan oleh dua lembaga lain, IMF dan WTO. Dan lagi-lagi, keputusan-keputusan yang dihasilkan di kedua lembaga itu setali tiga uang dengan Bank Dunia. Sampai-sampai, Joseph E Stiglitz, peraih Hadiah Nobel Ekonomi 2001 mengatakan bahwa Barat bersikap hipokrit dalam permainan ekonomi dunia. Stiglitz, yang juga warga negara Amerika mengatakan pada pertemuan WTO di Hongkong Desember 2005, bahwa negara berkembang, sama sekali tidak bisa menandatangani perjanjian perdagangan. Hal ini sama tidak adilnya seperti perundingan perdagangan di masa lalu. Barat memperlakukan barang-barang yang diproduksi di dalam negeri secara berbeda dengan barang- barang yang diproduksi di luar AS. Barat memiliki sebuah standar ganda
Tentang IMF, Stiglitz juga pernah mengucapkan kritikan pedas. Pada April 2001 ia mengatakan, “Ketika sebuah negara sedang terpuruk, IMF mengambil kesempatan dan memeras titik darah terakhirnya. IMF mengipasi api sehingga, akhirnya, seluruh kualinya meledak. Ia menyebabkan kematian banyak orang. Ia tak peduli orang hidup atau mati. Kebijakannya mengecilkan demokrasi… agak mirip dengan Zaman Pertengahan atau Perang Opium.”
Pada tahun 2002, Stiglitz menulis buku Globalization and Its Discontents, saat ia menegaskan bahwa IMF meletakkan kepentingan pemegang saham terbesar (Amerika Serikat) di atas kepentingan negara-negara miskin yang justru seharusnya ia bantu. Masih kata Stiglitz, dalam rangka menanggulangi krisis moneter yang dialami oleh beberapa negara Amerika Latin, bekerja sama dengan Departemen keuangan AS dan Bank Dunia, IMF sepakat meluncurkan sebuah paket kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai paket kebijakan Konsensus Washington. Agenda pokok paket kebijakan Konsensus Washington yang menjadi menu dasar program penyesuaian struktural IMF tersebut dalam garis besarnya meliputi : (1) pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi negara dalam berbagai bentuknya, (2) pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan, (3) pelaksanaan liberalisasi sektor perdagangan, dan (4) pelaksanaan privatisasi BUMN.
Di Indonesia, menyusul kemerosotan nilai rupiah tahun 1997, Pemerintah Indonesia kemudian secara resmi mengundang IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Sebagai syarat untuk mencairkan dana talangan yang disediakan IMF, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan paket kebijakan Konsensus Washington melalui penanda-tanganan Letter Of Intent (LOI), yang salah satu butir kesepakatannya adalah penghapusan subsidi untuk bahan bakar minyak, yang sekaligus memberi peluang masuknya perusahaan multinasional seperti Shell. Begitu juga dengan kebijakan privatisasi beberapa BUMN, diantaranya Indosat, Telkom, BNI, PT. Tambang Timah dan Aneka Tambang. Akhirnya hal ini menjadi momentum pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara lebih massif yang sebenarnya telah dimulai sejak pertengahan 1980-an.
Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. Paham ini memfokuskan pada metode pasar bebas, pembatasan yang sedikit perilaku bisnis, dan hak-hak milik pribadi. Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, dan atau intervensi militer. Pembukaan pasar merujuk pada perdagangan bebas. Neoliberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan politis multilateral, melalui berbagai kartel pengelolaan perdagangan seperti WTO dan Bank Dunia. Ini mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintahan sampai titik minimum. Neoliberalisme melalui ekonomi pasar bebas berhasil menekan intervensi pemerintah (seperti paham Keynesianisme), dan melangkah sukses dalam pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Untuk meningkatkan efisiensi korporasi, neoliberalisme berusaha keras untuk menolak atau mengurangi kebijakan buruh seperti upah minimun, dan hak-hak daya tawar kolektif.
Neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar, dengan pembenaran mengacu pada kebebasan. Seperti pada contoh kasus upah pekerja, dalam pemahaman neoliberalisme pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan gaji pekerja atau dalam masalah-masalah tenaga kerja sepenuhnya ini urusan antara si pengusaha pemilik modal dan si pekerja. Pendorong utama kembalinya kekuatan kekuasaan pasar adalah privatisasi aktivitas-aktivitas ekonomi, terlebih pada usaha-usaha industri yang dimiliki-dikelola pemerintah. Tapi privatisasi ini tidak terjadi pada negara-negara kapitalis besar, justru terjadi pada negara-negara Amerika Latin dan negara-negara miskin berkembang lainnya. Privatisasi ini telah mengalahkan proses panjang nasionalisasi yang menjadi kunci negara berbasis kesejahteraan. Nasionalisasi yang menghambat aktivitas pengusaha harus dihapuskan.
Revolusi neoliberalisme ini bermakna bergantinya sebuah manajemen ekonomi yang berbasiskan persediaan menjadi berbasis permintaan. Sehingga menurut kaum Neoliberal, sebuah perekonomian dengan inflasi rendah dan pengangguran tinggi, tetap lebih baik dibanding inflasi tinggi dengan pengangguran rendah. Tugas pemerintah hanya menciptakan lingkungan sehingga modal dapat bergerak bebas dengan baik. Dalam titik ini pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan memotong pengeluaran, memotong biaya-biaya publik seperti subsidi, sehingga fasilitas-fasilitas untuk kesejahteraan publik harus dikurangi.
Akhirnya logika pasarlah yang berjaya diatas kehidupan publik. ini menjadi pondasi dasar neoliberalisme, menundukan kehidupan publik ke dalam logika pasar. Semua pelayanan publik yang diselenggarakan negara harusnya menggunakan prinsip untung-rugi bagi penyelenggara bisnis publik tersebut, dalam hal ini untung rugi ekonomi bagi pemerintah. Pelayanan publik semata seperti subsidi dianggap akan menjadi pemborosan dan inefisiensi. Neoliberalisme tidak mengistimewakan kualitas kesejahteraan umum. Tidak ada wilayah kehidupan yang tidak bisa dijadikan komoditi barang jualan. Semangat neoliberalisme adalah melihat seluruh kehidupan sebagai sumber laba korporasi.
 Misalnya dengan sektor Sumber Daya Air, program liberalisasi sektor sumber daya air yang implementasinya dikaitkan oleh Bank Dunia dengan skema watsal atau water resources sector adjustment loan. Air dinilai sebagai barang ekonomis yang pengelolaannya pun harus dilakukan sebagaimana layaknya mengelola barang ekonomis. Dimensi sosial dalam sumberdaya public goods direduksi hanya sebatas sebagai komoditas ekonomi semata. Hak penguasaan atau konsesi atas sumber daya air ini dapat dipindah tangankan dari pemilik satu ke pemilik lainnya, dari satu korporasi ke korporasi lainnya, melalui mekanisme transaksi jual beli. Selanjutnya sistem pengaturan beserta hak pengaturan penguasaan sumber air ini lambat laun akan dialihkan ke suatu badan berbentuk korporasi bisnis atau konsorsium korporasi bisnis yang dimiliki oleh pemerintah atau perusahaan swasta nasional atau perusahaan swasta atau bahkan perusahaan multinasional dan perusahaan transnasional.
Misalnya dengan sektor Sumber Daya Air, program liberalisasi sektor sumber daya air yang implementasinya dikaitkan oleh Bank Dunia dengan skema watsal atau water resources sector adjustment loan. Air dinilai sebagai barang ekonomis yang pengelolaannya pun harus dilakukan sebagaimana layaknya mengelola barang ekonomis. Dimensi sosial dalam sumberdaya public goods direduksi hanya sebatas sebagai komoditas ekonomi semata. Hak penguasaan atau konsesi atas sumber daya air ini dapat dipindah tangankan dari pemilik satu ke pemilik lainnya, dari satu korporasi ke korporasi lainnya, melalui mekanisme transaksi jual beli. Selanjutnya sistem pengaturan beserta hak pengaturan penguasaan sumber air ini lambat laun akan dialihkan ke suatu badan berbentuk korporasi bisnis atau konsorsium korporasi bisnis yang dimiliki oleh pemerintah atau perusahaan swasta nasional atau perusahaan swasta atau bahkan perusahaan multinasional dan perusahaan transnasional.
Maka, melihat permainan ekonomi yang sedemikian rakus menempatkan negara-negara miskin dan berkembang sebagai mangsa negara-negara besar kapitalis, sudah selayaknya kita menakar ulang paradigma pembangunan ekonomi kita. Diakui atau tidak, penyelenggaraan pembangunan ekonomi Indonesia telah terjerat korporatokrasi seperti gambaran Perkins dan “terjajah” para lembaga pengusung ekonomi neoliberal seperti deskripsi Stiglitz.
Setelah menghapuskan korporatokrasi, tidak ada jalan lain kecuali mengelola sendiri (swakelola) kekayaan SDA kita. Lebih khusus dalam sektor pertambangan, karena penguasaan pihak asing di sektor ini, telah terjadi korupsi berskala besar. Dalam hal penguasaan pertambangan oleh pihak asing, menurut Tamagola (Kompas, 14/2/2005), telah terjadi pengaplingan atas daerah-daerah tambang di Indonesia. Kapling-kapling itu meliputi: Timika untuk Freeport, Lhok Seumawe untuk Exxon Mobil, Sulawesi Selatan untuk Mosanto, Buyat-Minahasa dan Sumbawa untuk Newmont International, Teluk Bintuni di Papua untuk British Petrolium, Kaltim untuk PT Kaltim Prima Coal, dsb. Pengaplingan tersebut menunjukkan telah terjadi persekongkolan antara penguasa dan kekuatan modal asing.
Amien Rais (Kompas, 5/1/2006) mengatakan, banyak proyek pertambangan yang perlu disoroti, antara lain yaitu PT Freeport Indonesia, tambang emas raksasa di Timika, Papua; Proyek Liquefied Natural Gas Tangguh yang dibangun di Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari, Papua; serta PT Newmont Minahasa Raya, pertambangan emas dan tembaga di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Informasi yang diperolehnya, kata Amien, areal yang sudah hancur ekologinya di daerah Freeport mencapai 200 kilometer persegi. Padahal, rakyat tak pernah tahu berapa puluh atau ratus ton emas dan perak yang sudah dibawa ke luar negeri. Tapi, anehnya, delapan tahun sebelum kontrak habis, kontrak karya sudah diperpanjang lagi.
Terkait dengan proyek Tangguh, kata Amien, saat ini sudah dikontrakkan dengan RRC selama 30 tahun. Harga gas dipatok secara flat 2,6 dollar AS per mbtu. Padahal, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari seorang ahli sudah mencapai 9 dollar AS. “Jadi, berapa ratus triliun rupiah kerugian kita,” ujarnya. Amien juga menyebut sejumlah perusahaan pengelolaan semen yang mayoritas sahamnya sudah jatuh ke tangan pihak asing, seperti Semen Cibinong, Semen Tiga Roda, Semen Gresik, maupun Semen Padang. Belum lagi pihak asing yang juga akan menguasai SPBU-SPBU.
Fakta ini harus diperhatikan oleh para pengambil kebijakan di republik ini. Suara vokal para tokoh masyarakat, janganlah dituding beraroma politis untuk mengguncang kekuasaan. Janganlah pemerintah suudzon (berburuk sangka) pada rakyatnya, karena semuanya demi keberlangsungan hidup dan kehidupan kita.
Menarik untuk mencermati ‘jeritan rakyat yang terdengar’ dalam jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada tanggal 22-23 Maret 2006 kemarin. Dalam publikasi hasil jajak pendapat itu (Kompas, 27/03/2006), dari sampel sebanyak 831 responden di 10 kota besar di Indonesia mulai Medan hingga Jayapura, terekam suara rakyat sebagai berikut:
☺ 71,5 persen responden menyatakan “tidak puas” dengan pemanfaatan hasil kekayaan tambang untuk kesejahteraan masyarakat.
☺ 72,2 persen responden menyatakan bahwa tindakan eksploitasi kekayaan alam Indonesia, khususnya sektor pertambangan oleh perusahaan-perusahaan asing merupakan “gejala yang berlebihan” dan “hanya menguntungkan asing”.
☺ 72,6 persen responden menyatakan bahwa “pemerintah terlalu lamban” dan “tidak tegas menindak” perusahaan-perusahaan asing yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam eksploitasi pertambangan.
☺ 54,5 persen responden menyatakan pemerintah cenderung “berpihak pada pemilik modal asing dibandingkan rakyatnya sendiri”, hal ini tercermin dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan selama ini.
☺ 77,5 persen responden menyatakan “sangsi” bahwa keberadaan perusahaan-perusahaan asing penguasa pertambangan yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia itu dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat sekitarnya.
☺ 78,5 persen responden menilai kehadiran perusahaan pertambangan asing “lebih banyak membawa dampak buruk bagi lingkungan hidup” masyarakat sekitar area pertambangan.
☺ Tak pelak, sebanyak 89,9 persen responden SETUJU jika kontrak kerja yang mengatur bagi hasil antara perusahaan asing, pemerintah dan masyarakat lokal “ditinjau kembali”.
Walaupun hasil jajak pendapat itu tidak dimaksudkan untuk mewakili pendapat seluruh rakyat di negeri ini, namun setidaknya bisa memberikan gambaran bahwa rakyat sudah cukup muak dengan kehadiran perusahaan-perusahaan asing pertambangan di Indonesia yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Sudah seharusnya pemerintah mendengar jeritan ini dengan membuka telinga lebar-lebar dan mencernanya dengan pikiran yang jernih. Sungguh tidak ada motif dibalik seruan dan suara itu, kecuali “ini menyangkut keberlanjutan hidup dan kehidupan kita”.
Masih dari hasil jajak pendapat itu, 69,3 persen responden menyatakan bahwa kita masih membutuhkan keterlibatan asing dalam pengelolaan pertambangan. Mereka menyatakan bahwa teknologi dan SDM kita masih belum mampu untuk mengelolanya. Keresahan awam ini dijawab oleh para pakar. Jika alasannya adalah teknis pengelolaan, Batubara mengatakan bahwa dalam hal kemampuan teknis, Pertamina sudah punya banyak pengalaman eksplorasi, seperti di Tuban (Sumur Sukowati); Bekasi (Tambun dan Pondok Tengah) Patrol, Jawa Barat; Prabumulih, Sumsel, dan lain-lain. Profil daerah-daerah itu hampir sama dengan Blok Cepu: eksplorasi on-shore, sumur dangkal, flow minyak bersifat natural, dan tak butuh teknologi tinggi. Belum lagi dari tingkat efisiensi, di mana biaya pengeboran dan operasional Pertamina jelas lebih murah. (Republika, 6/3/2006). Utomo bahkan menandaskan, sebetulnya, jika landasannya murni bisnis, Pertamina sanggup. Soal biaya, siapa lembaga keuangan yang tidak tergiur dengan keuntungan Cepu? Soal kemampuan, Pertamina punya pengalaman–kalaupun kurang, panggil saja ahli perminyakan yang bekerja di perusahaan asing. Begitu juga teknologi, ibaratnya kalau tidak punya, tinggal beli (Republika, 15/3/2006).
Jadi sebenarnya kita mampu, tinggal mau apa tidak memulainya. Niat ini yang harus dimulai oleh pemerintah. Pemerintah harus segera beritikad untuk mengembalikan pengelolaan seluruh kekayaan alam kita, utamanya kekayaan tambang, kepada anak-anak bangsa. Sudah saatnya kita ‘mencangkul sawah kita sendiri’. Jangan lagi pemerintah abai terhadap permasalahan ini, karena rakyat bukan sekumpulan manusia bodoh yang gampang dikibuli dengan janji-janji manis yang pepesan kosong semata. Karena, 61,7 persen responden dalam jajak pendapat Kompas tersebut menuding “pemerintah belum serius” mengembangkan teknologi pengelolaan hasil kekayaan alam kita sendiri.
Kalau Sukarno pernah mengatakan tentang harus sangat selektifnya kita menerima penanaman modal asing (PMA) dalam pengelolaan SDA. Bahkan jika kita belum mampu mengelola, ”Kita simpan di bawah tanah sampai para insinyur kita mampu menggarapnya sendiri,” katanya. Tapi Bung, kita sudah mampu sekarang. Jadi persoalannya bukan kemampuan, tapi kemauan. Kalo masih ada saja pihak yang enggan dengan swakelola SDA kita, ingatlah klimaks yang diperlihatkan dalam pidato founding fathers Indonesia yang lain, Bung Hatta. Dia menegaskan, “Camkanlah! Negara Republik Indonesia belum lagi berdasarkan Pancasila, apabila pemerintah dan masyarakat belum sanggup menaati Undang-undang Dasar 1945, terutama belum dapat melaksanakan pasal 27 ayat 2, pasal 31, pasal 33 dan pasal 34. Dan camkanlah pula, bahwa (nilai-nilai) Pancasila itu adalah kontrak Rakyat Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Angkatan muda sekarang tidak boleh melupakan ini dan mengabaikannya! Sekian.”
Paradigma Collective Property
Penjualan aset-aset bangsa oleh pemerintahnya sendiri tidak terlepas dari pertentangan paham kepemilikan. Perspektif terhadap pertambangan, seperti halnya air, dapat mengadopsi tabulasi yang disusun Perdana (2003):
| Perspektif | Negara | Pemilik Modal | Rakyat |
| Politik | State Based | Fasilitasi regulasi state | Community based |
| Ekonomi | Capital Based (investasi/ privatisasi/utang) | Jaminan pembengkakan capital/investasi (industri tambang/ komoditas) | Jaminan sumberdaya dipergunakan untuk kesejahteraan |
| Sosial | Rakyat sebagai Obyek (Uniformitas) | Mementingkan diri sendiri (Filantropi sebagai hipokrisi) | Kebersamaan/ collectivity |
| Budaya | Perilaku eksploitatif, ekspansif | Monopoli, eksploitatif dan ekspansif | Etika lingkungan sebagai sistem lokal (lokal knowledge & wisdom) |
| Ekologi | Eco-Developmentalism | Eco-Proseduralism | Eco-Populism |
Dengan perbedaan perspektif yang demikian, yang terjadi adalah konflik yang berkelanjutan. Dalam perspektif kapitalisme dan ekonomi neoliberal seperti diatas, maka isu privatisasilah yang mendominasi. Privatisasi inilah yang menghadapkan sumberdaya yang menguasai hajat hidup manusia versus subyek kepemilikan untuk diperdagangkan. Ini sama halnya mempertentangkan komunitas publik versus sekelompok pemilik modal. Hasilnya, 5 jiwa melayang di Abepura pada bentrok antara (aparat) negara yang membela ‘hak-hak keamanan’ pemilik modal (baca: Freeport) dan masyarakat. Yang rugi bukan pemilik modal, tapi lagi-lagi masyarakat.
‘Keberhasilan’ konspirasi antara lembaga-lembaga keuangan internasional (Multilateral Development Bank’s/MDB’s), korporasi-korporasi transnasional (TNCs) milik negara maju, Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) untuk menggasak rakyat miskin telah terjadi di mana-mana. Lebih dari 10 tahun lalu sebenarnya konspirasi tersebut dilakukan dengan membangun jalan memuluskan privatisasi sebagai kondisionalitas pemberian utang ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Plus, didorong dengan perjanjian perdagangan yang mendesak negara pengutang menderegulasi sektor air dan membukanya bagi investasi asing. Liberalisasi sektor publik merupakan konsekuensi logis setelah liberalisasi modal, barang dan jasa yang dilakukan secara bertahap mulai 1970-an. Perluasan pasar dan pangsa pasar merupakan cita-cita para kapitalis monopolistik agar bisa mempertahankan dominasinya. Ironinya, pemerintah lebih terkesan sebagai pelayan korporasi asing, bukan pelayan rakyat.
Dilihat dari perspektif kepemilikan tanah, secara legal formal, Indonesia tidak lagi menganut asas domein verklaring. Domein verklaring dengan arti bahwa semua tanah-tanah tidak dapat dibuktikan siapa pemiliknya adalah menjadi tanah negara, hanya diterapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di Indonesia. Kalo (2004) mengatakan bahwa dengan diberlakukannya asas domein verklaring oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, dapat diasumsikan bahwa kebijakan itu didasari atas alasan-alasan karena pemerintah Belanda menganggap raja-raja di Indonesia yang mempunyai kekuasaan hak domein atas tanah, maka dengan sendirinya hak domein itu juga diambil over oleh Belanda karena Belanda memegang kedaulatan di Indonesia. Padahal, anggapan pemerintah Belanda yang demikian itu, pada dasarnya adalah sangat keliru. Karena tidak semua raja-raja di Indonesia mempunyai hak domein atas tanah di wilayah kerajaannya. Bahkan di wilayah persekutuan hukum adat yang berada di bawah kekuasaan kesultanan, tanah adalah merupakan milik komunal (beschikkingsrecht).
Oleh sebab itu asas domein verklaring ini tidak bisa dipakai alasan pemerintah untuk menjual area pertambangan yang menguasai hajat hidup orang banyak kepada segelintir pemilik modal. Negara dalam hal ini harus merujuk pada pasal 1 UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan yang menyebutkan “Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesiayang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Jelas dari pendekatan legal formal, sesuai dengan tujuan negara bonum publicum, negara bertanggung jawab untuk mengelola kepemilikan umum (collective property) untuk kepentingan rakyat banyak, memanfaatkan sumber-sumber pendapatan negara untuk rakyat, menciptakan situasi perekonomian yang kondusif seperti keluasan lapangan kerja dan kemampuan yang tinggi dari para pekerja (profesionalitas). Paradigma ini harus menjadi mindset dalam pengelolaan SDA kita, baik itu menjadi paradigma pemerintah, para pengusaha nasional ataupun masyarakat.
Tidak ada lagi grey area dalam ranah hukum Indonesia tentang kedudukan bahan tambang, mineral, energi bahkan juga air sebagai milik umum. Negara hanya berhak untuk menjadi regulator dan dipergunakan sebesar-besar untuk kesejahteraan rakyat. Penyimpangan dari garis ini adalah pelanggaran hukum. Bahkan Agustianto mengatakan sebagai “keharaman”. Dalam hal ini dia menawarkan pendekatan lain, yaitu pendekatan sosio-religius, dimana pemerintah dan rakyat harus memahami “fikih sumber daya alam/SDA’, sesuai dengan aturan agama bahwa sumber daya alam yang termasuk milik umum seperti air, api, padang rumput, hutan dan barang tambang harus dikelola hanya oleh negara yang hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer semisal, pangan, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum.
Pendekatan sosio-religius ini, mengedepankan konsep kepemilikan yang jelas, dimana tambang yang jumlahnya sangat besar, baik yang tampak sehingga bisa didapat tanpa harus bersusah payah seperti garam, batubara, dan sebagainya ataupun tambang yang berada di dalam perut bumi yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan usaha keras seperti tambang emas perak, besi, tembaga, timah dan sejenisnya baik berbentuk padat semisal kristal ataupun berbentuk cair, semisal minyak, termasuk milik umum. Barang-barang tambang adalah milik orang banyak meskipun diperoleh dari tanah hak milik khusus. Karena itu, siapa saja yang menemukan barang tambang atau minyak bumi pada tanah miliknya, dilarang baginya untuk memilikinya dan barang tambang tersebut harus diberikan kepada negara untuk dikelola. Pemerintah harus memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya alam tersebut untuk kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat umum (Waspada, 16/12/2005).
Menyangkut masalah contract of work (CoW) atau lebih populer disebut kontrak karya, menarik untuk mencermati usulan Fahmi Amhar, Peneliti Utama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). Amhar (RRI-Online, 7/2/2006) meminta pemerintah untuk memanfaatkan sistem syariah dalam menandatangani kontrak karya pertambangan. Pengelolaan pertambangan dengan sistem syariah tersebut menandaskan bahwa hutan dan barang tambang adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara. Hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya.
Pendekatan legal-formal lewat sistem syariah ini bisa dijadikan alternatif pemecahan. Apalagi UU kita telah banyak diwarnai oleh sistem syariah yang terbukti memiliki dampak yang lebih baik dibandingkan ‘sistem konvensional’. Siapa tahu, peninjauan ulang berbasis syariah terhadap UU Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967 yang salah satu pasalnya memberikan jalan bagi masuknya investasi asing di bidang pertambangan (lihat pasal 8 UU No 11 tahun 1967) dan UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan, yang semakin mengukuhkan jalan bagi investasi asing di bidang mineral, bisa mengembalikan hasil kekayaan tambang kita ini untuk kehidupan kita sendiri. Dalam UU baru ini nanti, pengelolaan sumber daya alam milik umum yang berbasis swasta harus diubah menjadi pengelolaan kepemilikan umum oleh negara. Tentu dengan tetap berorientasi kepada kelestarian sumber daya alam tersebut, hasil pengelolaan tambang ini dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Negara sebagai Pelayan Publik
Dengan paradigma bahwa negara dan pemerintahan adalah pelayan publik, maka derivat-derivat dari permasalahan pertambangan akibat pengelolaan yang kapitalistik akan tereduksi.
Tentang permasalahan bencana misalnya, angka-angka bencana akan terpangkas dengan pengelolaan yang terencana, berbasis rakyat dan berorientasi kesejahteraan umum. Seperti yang dicatat Bakornas PB, sejak tahun 1998 hingga pertengahan 2003, tercatat telah terjadi 647 kejadian bencana di Indonesia, di mana 85% dari bencana tersebut merupakan bencana banjir dan longsor. Persentase tersebut berarti bahwa bencana terbesar yang terjadi justru bencana yang bisa diatasi, diantisipasi kejadian dan resikonya. Bencana banjir dan tanah longsor adalah bencana yang terjadi bukan hanya karena faktor alamiah alam, namun lebih banyak karena campur tangan manusia. Bencana banjir dan tanah longsor merupakan bencana yang “bisa direncanakan”.
Bencana Alam di Indonesia (1998-2003)
| Jenis | Jumlah Kejadian | Korban Jiwa | Kerugian (juta rupiah) | ||
| Banjir | 302 | 1066 | 191.312 | ||
| Longsor | 245 | 645 | 13.928 | ||
| Gempa bumi | 38 | 306 | 100.000 | ||
| Gunung berapi | 16 | 2 | n.a | ||
| Angin topan | 46 | 3 | 4.015 | ||
| Jumlah | 647 | 2022 | |||
Sumber: Bakornas PB.
Seperti halnya catatan Walhi (2004), banjir dan longsor di Bukit Lawang, Bohorok 2003, banjir dan kekeringan di kawasan ekosistem Leuser, banjir bandang di Jawa Tengah dan Langkat 2003, longsor di Mandalawangi Garut 2003, banjir dan longsor di NTT 2003, kebakaran hutan di Palangkaraya, dan kekeringan di seluruh pulau Jawa, semuanya disebabkan karena mismanagement dan human error. Artinya, dengan paradigma pembangunan yang eksploitatif dan kapitalistik, keseimbangan ekosistem akan terganggu akibat penambangan massif, illegal logging, kongkalikong (oknum?) pemerintah dengan perusahaan eksplorasi swasta lokal ataupun asing. Walhi menyebut sebagai ‘sejuta bencana terencana di Indonesia’.
Dengan paradigma pengelolaan SDA yang berbasis kesejahteraan umum, maka penyebab bencana akan tereduksi hingga pada tingkat penyebab yang diluar kuasa manusia, atau faktor natural menyangkut aspek hidrologi (air bawah tanah dll.), meteorologi (kecuacaan) dan geologi (pergeseran lempeng, tsunami dll.). Sementara itu penyebab yang lain menyangkut faktor legal-formal (agraria dll.), faktor tekno-kultural (tata-ruang, tata guna lahan, perencanaan kawasan dll.), hingga faktor sosio-politik (korporatokrasi, kapitalisme, kelalaian penguasa dll.) akan dengan sendirinya tereduksi.
Tidak hanya itu saja, bahkan untuk memperkecil pencetus terjadinya bencana akibat faktor natural, negara akan berusaha memperkecil (jika tidak bisa meniadakan) kerugian yang mungkin akan terjadi melalui manajemen bencana yang sistematis. Pengadaan peta-peta tematik kebencanaan hingga spot-spot yang detail, juga mitigasi baik secara struktural maupun non-struktural, akan dilakukan oleh negara yang ‘menyayangi’ rakyatnya. Dengan kesiapan pemerintah beserta seluruh aparatnya, dampak negatif bencana akan sangat terbatas mengemuka.
Demikian pula dengan permasalahan ekologi. Tanpa perlu repot-repot mengadakan kampanye cinta lingkungan, atau memainkan spiritualitas baru yang menganggap lingkungan sebagai ‘tuhan’ yang menentukan hidup matinya komunitas manusia, dengan paradigma pembangunan yang berbasis kesejahteraan umum, maka keseimbangan lingkungan akan terjadi dan keberlangsungan ekologi akan tercapai. Secara otomatis, keberlanjutan kehidupan anak manusia juga akan terjamin.
Kemudian menyangkut pelanggaran terhadap sumber-sumber kehidupan masyarakat, itupun tidak akan terjadi. Negara yang cinta rakyatnya akan menghormati hak-hak kepemilikan individu yang memang menjadi hak asasi alamiah manusia. Negara mengormati kepemilikan pribadi (individual property) yang didapatkan dengan cara-cara yang sah, legal dan halal. Bahkan negara akan menjamin keamaanan kepemilikan individu itu jika menghadapi ancaman atau gangguan dari individu, kelompok atau bahkan negara lain. Kehilangan jiwa seorang individu saja, bahkan harta kekayaan yang sah seorang individu yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan pihak lain akan mengakibatkan negara membela dengan segera dan menyelesaikannya secara jantan. Maka dalam hal ini tidak akan terjadi perampasan tanah pribadi atas nama ‘kepentingan umum’ untuk kepentinngan korporat-korporat
pertambangan misalnya, atau tidak akan muncul konflik Buyat yang menempatkan rakyat Buyat seolah-olah sebagai anak tiri (atau anak yatim?) pemerintah.
Kasus-kasus pelecehan terhadap perempuan juga tidak akan terjadi. Wanita sebagai tiang negara akan menjadi asas negara yang mencintai rakyatnya. Kasus pemerkosaan, pembunuhan, penularan penyakit-penyakit berbahaya, pembayaran upah yang tertunda dan minimalis tidak akan terjadi. Negara yang cinta rakyatnya akan menempatkan perempuan sesuai dengan kedudukannya yang mulia. Kedudukan perempuan bukan sebagai the second level, karena perempuan memiliki peran yang luar biasa penting. Penyiapan generasi penerus yang kuat, cerdas dan berkualitas sangat tergantung dari peran para perempuan. Dimata hukum perempuan juga tidak dipandang sebelah mata, dia akan ditempatkan sesuai dengan kapasitasnya. Dalam ranah privat dan publik perempuan akan menjadi mitra yang harmonis bagi laki-laki. Semua itu terjadi jika pembangunan SDM dan SDA yang dilakukan negara berbasis kesejahteraan dan bukan berparadigma kapitalistik. Paradigma kapitalistik menyebabkan posisi perempuan sebagai obyek pemuas nafsu laki-laki, sebagai binatang pelengkap dan bahkan tidak dianggap apa-apa.
Yang terakhir dari segi pemenuhan hak-hak kewarganegaraan. Paradigma pengelolaan SDA oleh negara yang cinta rakyatnya akan mengacu pada tujuan dibentuknya negara, yaitu kebahagiaan rakyat (bonum publicum). Perlu diingat pernyataan Dwitunggal Indonesia. Sukarno pernah mengatakan, “Jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, paham tolong-menolong, paham gotong-royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap paham individualisme dan liberalisme daripadanya.” Hatta meneruskan, “Walaupun yang dibentuk itu negara kekeluargaan, namun jangan lupa beberapa hak dari warga negara, jangan sampai timbul negara kekuasaan (machtsstaat/negara penindas).”
Semua hal itu akan terealisasi jika negara berparadigma kesejahteraan umum. Kepemilikan individu dihormati dan diamankan, kepemilikan umum akan dikelola oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan negara hanya memiliki aset-aset yang tidak bisa menjadi hal milik individu namun juga tidak menjadi hajat hidup orang banyak seperti pantai, tanah gersang/mati dll. Negara yang demikian itu akan benar-benar menjadi negara yang mencintai rakyatnya dan negara yang dicintai rakyatnya. Bagaimana Indonesia masa depan?
Menuju Masa Depan Gemilang
 Dengan menempatkan aset-aset sesuai dengan konsep kepemilikan yang tepat, paradigma pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bersama, maka pengelolaan pertambangan mineral dan energi akan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama dan menjamin keberlanjutan keseimbangan ekologis dan kehidupan umat manusia. Paradigma kapitalistik, neoliberalistik dan korporatokrasi harus segera dibersihkan dari otak-otak penyelenggara pemerintahan dan juga rakyat. Kemandirian, kepercayaan diri dan keberanian untuk lepas dari pengaruh asing juga harus segera dibentuk pada jiwa-jiwa anak bangsa. Semuanya itu jika kita semua menginginkan Indonesia yang besar di masa mendatang. Indonesia yang bersatu, yang mandiri, dan yang benar-benar merdeka.
Dengan menempatkan aset-aset sesuai dengan konsep kepemilikan yang tepat, paradigma pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bersama, maka pengelolaan pertambangan mineral dan energi akan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama dan menjamin keberlanjutan keseimbangan ekologis dan kehidupan umat manusia. Paradigma kapitalistik, neoliberalistik dan korporatokrasi harus segera dibersihkan dari otak-otak penyelenggara pemerintahan dan juga rakyat. Kemandirian, kepercayaan diri dan keberanian untuk lepas dari pengaruh asing juga harus segera dibentuk pada jiwa-jiwa anak bangsa. Semuanya itu jika kita semua menginginkan Indonesia yang besar di masa mendatang. Indonesia yang bersatu, yang mandiri, dan yang benar-benar merdeka.
Maka, teringatlah gelegar orasi Bung Karno, “Sungguh, kamu bukan bangsa cacing, kamu adalah bangsa berkepribadian banteng! Hayo, maju terus! Jebol terus! Tanam terus! Vivere Pericoloso! Ever onward, never retreat! Kita pasti menang.”*** (Juara I Lomba Karya Tulis Nasional Tambang dan Bencana 2006 – Jatam, Walhi, Pokja PSDA) ***Ninunery@gmail.com
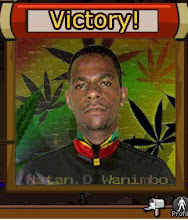

Tidak ada komentar:
Posting Komentar